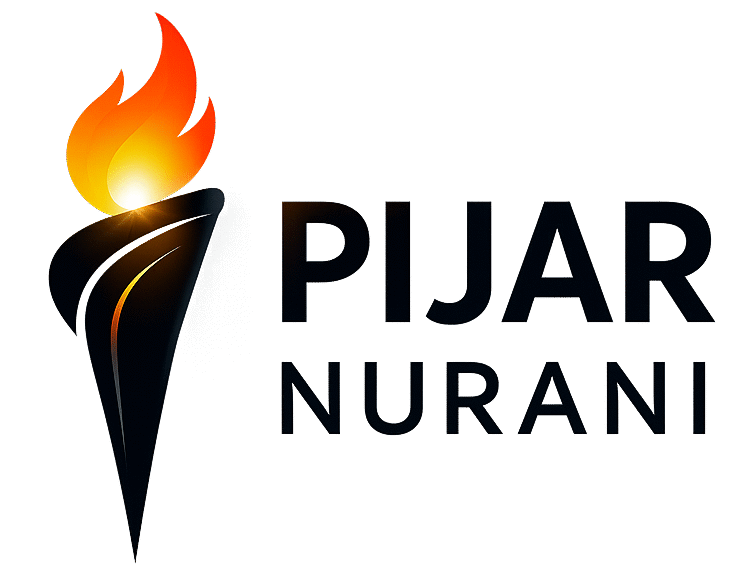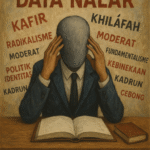Literasi & Negara Gagal

Dungu, Literasi, dan Negara Gagal
Rocky Gerung adalah sosok yang selama ini kerap melontarkan kata “dungu.” Dalam berbagai kesempatan, ia mengucapkannya dengan fasih dan tanpa ragu. Sasaran utamanya adalah kekuasaan, atau siapa pun yang tidak mampu bernalar secara logis.
Bersamaan dengan itu, Rocky juga mempopulerkan istilah “akal sehat” sebagai lawan dari “dungu.” Filsuf yang satu ini mengajak publik untuk berpihak pada nalar sehat. Ia seolah ingin mengatakan bahwa musuh utama bangsa hari ini adalah kedunguan.
Hari-hari ini, perdebatan di ruang publik sering kali tidak mengedepankan kekuatan akal sehat. Pertengkaran yang ramai—terutama di panggung media sosial—lebih sering mengarah pada adu sentimen ketimbang pertukaran argumen. Antar-tesa tak berdialektika menjadi sintesa. Percakapan hanya berputar tanpa melahirkan gagasan baru yang segar.
Barangkali, itulah bentuk nyata dari kedunguan. Dungu adalah istilah untuk menyatakan ketidakmampuan menggunakan penalaran secara benar. Antara premis dan kesimpulan tidak nyambung, atau terjadi inkonsistensi logika. Dalam banyak percakapan, tampaknya banyak orang tidak memperhatikan disiplin bernalar ini. Dan itu, menurut Rocky, adalah dungu.
Terlepas dari apa yang dikatakan Rocky, kita memang memiliki pengalaman buruk terkait tradisi intelektual. Salah satu faktor utama adalah rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. UNESCO pernah menempatkan Indonesia pada posisi kedua terbawah di dunia dalam hal literasi. Hanya satu dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Sebuah angka yang amat mengkhawatirkan.
Rendahnya daya baca ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum. Ironisnya, kelompok terdidik pun mengalami hal yang sama. Dalam dua dekade terakhir, kemampuan literasi siswa-siswa Indonesia juga berada di posisi terbawah dunia. Demikian hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment) yang terkenal itu. Sejak tahun 2000 hingga 2018, survei yang diinisiasi oleh OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) secara konsisten menempatkan siswa Indonesia jauh di bawah rata-rata global.
Tak hanya literasi, survei PISA juga menempatkan Indonesia pada posisi buncit dalam kemampuan matematika. Padahal, rendahnya kemampuan matematika bukan semata soal berhitung dan angka. Matematika erat kaitannya dengan logika dan proses bernalar. Maka jika hasil riset menunjukkan lemahnya pemahaman matematika, itu berarti ada masalah pula dalam kemampuan bernalar siswa—atau bahkan nalar kolektif generasi.
Ironi lain yang mencolok: Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Rata-rata, pengguna gadget di Indonesia menghabiskan waktu hingga sembilan jam sehari. Angka yang luar biasa besar. Namun, tingginya penggunaan internet ternyata tidak berbanding lurus dengan kemampuan literasi. Di dalam gadget kita sebenarnya terdapat perpustakaan raksasa yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja secara gratis. Sayangnya, kehadiran perpustakaan digital itu belum mampu mendongkrak mutu literasi masyarakat.
Begitu pula halnya dengan kegiatan belajar di sekolah. Setiap hari siswa masuk sekolah, tetapi banyak yang tidak menjalani aktivitas membaca yang bermakna. Artinya, siswa tidak mendapat asupan pendidikan yang cukup. Ini sebuah ironi—kalau tidak boleh disebut tragedi—ketika sekolah tidak berbanding lurus dengan daya literasi dan kemampuan berpikir logis para siswanya.
Kondisi rendahnya literasi ini tentu berkaitan pula dengan tingkat kecerdasan. Menurut Healthline, IQ rata-rata manusia adalah 100, dengan sekitar 68% berada pada rentang IQ 85–115. Namun, riset World Population Review yang dilakukan oleh peneliti dari Ulster Institute menunjukkan bahwa rata-rata IQ masyarakat Indonesia hanya 78,49—menempatkan Indonesia di peringkat 130 dunia. Skor ini sedikit di bawah Kuwait (78,64) dan di atas Ekuador (78,26).
Secara metodologis, hasil riset tersebut tentu bisa diperdebatkan. Namun setidaknya, data itu memberi gambaran awal mengenai kondisi kecerdasan kolektif bangsa. Sama seperti berbagai survei literasi lainnya, rendahnya IQ orang Indonesia tampaknya mengonfirmasi lemahnya tradisi membaca dan bernalar selama ini.
Pertanyaan penting pun muncul: mengapa kondisi ini bisa terjadi? Apa penyebabnya?
Jawaban atas pertanyaan ini tentu kompleks dan panjang. Namun, salah satu faktor penting yang tak bisa diabaikan adalah lemahnya fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selama ini, mayoritas generasi muda Indonesia mengakses pendidikan melalui sekolah. Kualitas keterpelajaran masyarakat dibentuk melalui sistem pendidikan yang berada di bawah kendali negara. Hampir semua kebijakan pendidikan, dari hulu ke hilir, berada dalam tangan pemerintah.
Jika hasil riset kemudian menunjukkan rapor merah dalam bidang pendidikan, maka negara tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jika kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya—rendahnya literasi dan IQ kolektif—maka negara boleh dikatakan gagal menjalankan amanat konstitusi.