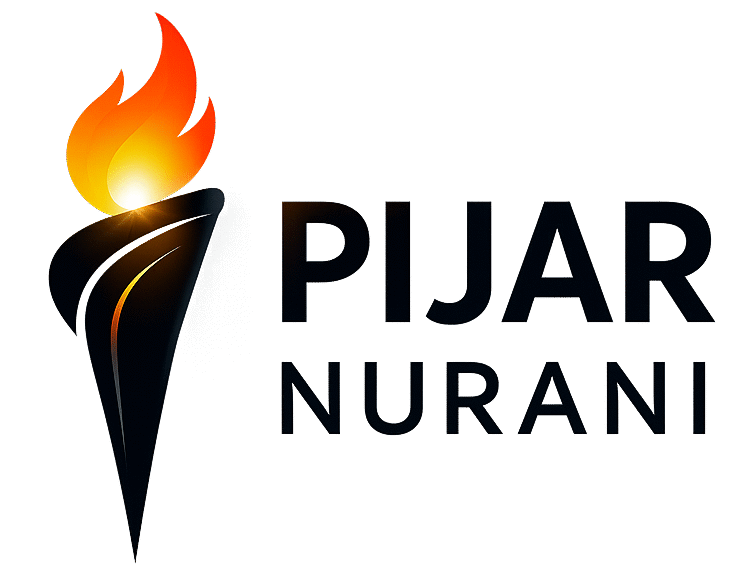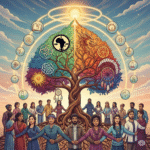Kisah Pembunuh Tuhan

Cendekiawan dan Kisah Pembunuh Tuhan
Tuhan? Tak ada itu. Tuhan telah mati!
Begitu ucap Friedrich Nietzsche, filsuf asal Jerman abad ke-19. “Mati” dalam ucapannya bukan dalam arti harfiah, melainkan sindiran tajam—semacam olok-olok terhadap zaman.
Bagi Nietzsche, agama telah kehilangan relevansinya. Di masa itu, masyarakat Eropa mulai meninggalkan peran agama dalam kehidupan. Keberadaan agama dianggap merendahkan potensi dan kemampuan manusia. Ketika manusia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, maka peran agama—dan juga Tuhan—dianggap selesai.
Dampak dari “kematian Tuhan” itu, menurut Nietzsche, adalah krisis nilai. Ia menyebutnya sebagai nihilisme. Nietzsche berpandangan bahwa manusia harus menciptakan nilai dan makna baru, tanpa harus bergantung pada konsep religius lama.
Senada dengan Nietzsche, Auguste Comte menyampaikan pandangan yang lebih halus tapi tak kalah tajam. Menurut bapak sosiologi itu, agama dan Tuhan hanyalah produk dari pikiran manusia yang tak berdaya menghadapi alam. Dalam ketakberdayaan itu, manusia menciptakan keyakinan terhadap adanya kekuatan di luar dirinya yang dianggap Mahakuasa dan menentukan segalanya.
Teori evolusi pemikiran Comte—yang berpuncak pada positivisme—seolah menjadi keranda bagi agama dan Tuhan. Keranda itu diusung menuju pemakaman untuk dikubur selama-lamanya. Di atas makam itu, seolah terukir nisan bertuliskan kutipan Nietzsche: “Tuhan telah mati.” Positivisme memulihkan kepercayaan manusia kepada dirinya sendiri untuk menentukan nasib dan arah hidupnya.
Sementara itu, Immanuel Kant, pemikir besar lainnya, menyampaikan pandangan yang tak kalah nyinyir terhadap konsep Tuhan. Dalam bahasa sederhana, ia seperti berkata: berhentilah mencoba membuktikan keberadaan Tuhan—itu mustahil. Secara epistemologis dalam sains, Tuhan tidak bisa dibuktikan. Kant menyebut Tuhan berada di wilayah noumenon, yaitu realitas yang memiliki logikanya sendiri, yang tidak bisa disentuh oleh indra dan pengalaman manusia.
Meski begitu, Kant tidak menolak pentingnya Tuhan. Menurutnya, Tuhan adalah sebuah ide atau postulat praktis yang relevan untuk menopang tatanan moral. Artinya, kita perlu mengandaikan Tuhan ada, agar moralitas masuk akal. Postulat ini bukan pengetahuan teoritis, melainkan kebutuhan praktis dalam kehidupan masyarakat yang beradab.
Masih banyak cendekiawan Eropa kala itu yang memiliki pandangan serupa. Mereka menandai kelahiran suatu zaman baru: abad pencerahan (Aufklärung). Sebuah era di mana manusia melepaskan diri dari masa kegelapan (otoritas tradisional) menuju zaman modern. Era ketika akal dan pengetahuan menjadi pusat orientasi hidup.
Kita, sebagai bangsa yang religius, tidak memiliki sejarah yang sama seperti Eropa pada abad pertengahan. Kritik keras terhadap agama dan Tuhan di Eropa bisa dipahami sebagai reaksi psikologis terhadap praktik keagamaan yang otoriter dan menindas. Banyak pemuka agama saat itu menafsirkan kebenaran secara tunggal, menyingkirkan yang berbeda, bahkan menghukum atau membunuh para cendekiawan yang dianggap menyimpang.
Serangan balik pun tak terelakkan. Bukan hanya institusi agama yang menjadi sasaran kritik, bahkan Tuhan pun “dikudeta dan dijatuhkan”. Paham teosentrisme (Tuhan sebagai pusat) tumbang, digantikan oleh antroposentrisme (manusia sebagai pusat). Tahta Tuhan diduduki oleh manusia. Dari sanalah, lahir semangat humanisme modern.
Lalu, bagaimana dengan keadaan bangsa ini?
Negeri ini tidak pernah mengalami sejarah yang sedramatis Eropa abad pertengahan. Tidak ada konflik serius yang memicu perubahan sosial secara radikal. Tak ada pertarungan intelektual antara pemuka agama dan kaum cendekiawan.
Namun kini, kita menyaksikan fenomena yang mirip secara esensial, meskipun tidak lahir dari pergulatan intelektual. Yang terjadi adalah serangkaian perilaku yang seakan-akan ingin menyatakan bahwa Tuhan tak ada. Banyak kaum terpelajar—terutama yang duduk di kekuasaan atau dekat dengan pusat kekuasaan—secara tidak langsung seperti meneriakkan kalimat Nietzsche: “Tuhan telah mati.” Bahkan, seolah mereka tengah beramai-ramai membunuh Tuhan.
Sepeninggal “Tuhan”, mereka merasa bebas melakukan apa saja.
Perampokan uang rakyat (korupsi), penyalahgunaan wewenang, hingga pembuatan kebijakan yang melukai rasa keadilan, dilakukan tanpa rasa sesal atau bersalah. Ironisnya, sebagian besar pelaku kejahatan yang sudah terbukti secara hukum justru berasal dari kalangan terpelajar.
Apa yang pernah digagas Kant—bahwa Tuhan bisa menjadi postulat moral masyarakat—ternyata tak efektif. Korupsi, yang kini menjadi “tradisi” dari kalangan elit hingga akar rumput, seolah menjadi simbol bahwa Tuhan telah dikubur dalam pemakaman yang sunyi. Agama memang masih ramai—gaduh di ruang publik dan sibuk dengan simbol—tapi dalam laku kehidupan, keberadaan Tuhan telah disangkal.
Ada semacam kekafiran kolektif, bukan dalam bentuk keyakinan, melainkan dalam bentuk praktik dosa yang terus-menerus dan tanpa henti.
Juni 2024