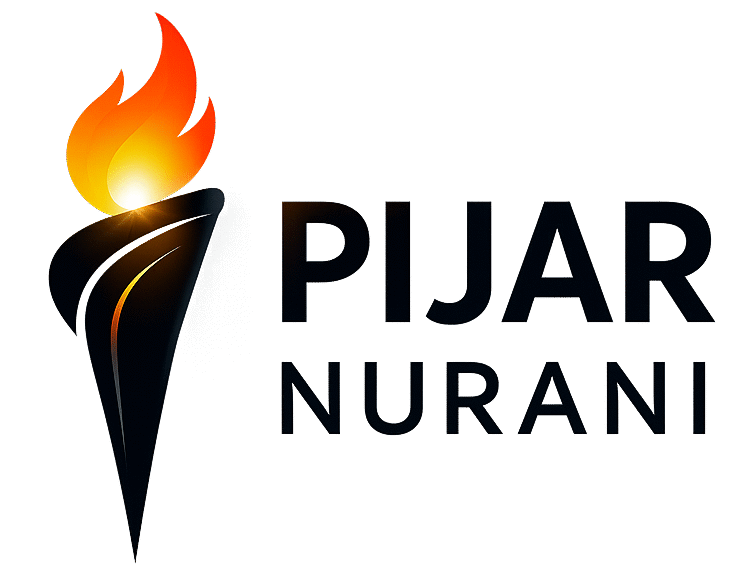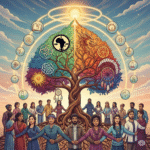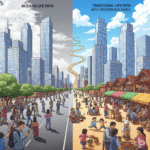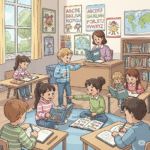Pesona Jawa

Derap modernisasi sedikit banyak telah menggerus budaya lokal. Sebagian warisan budaya bahkan nyaris rata dengan tanah. Sebagian lainnya bertahan, meski tertatih dan sempoyongan. Salah satu budaya lokal yang semakin tergerus adalah budaya Jawa. Tak sedikit masyarakat Jawa kini justru terpesona oleh budaya Barat dan perlahan meninggalkan budayanya sendiri.
Ironisnya, di saat yang sama, fenomena sebaliknya terjadi. Banyak masyarakat Barat justru jatuh hati pada budaya Timur, khususnya budaya Jawa. Mereka mempelajari kebudayaan Jawa dalam berbagai bentuk—mulai dari bahasa, tari, gamelan, wayang, hingga menjadi sinden atau dalang, perangkat penting dalam pertunjukan wayang kulit.
Ketertarikan orang Barat terhadap budaya Jawa bukanlah hal baru. Sejak abad ke-19, budaya Jawa sudah memikat perhatian para cendekiawan dan peneliti Eropa. Salah satunya adalah Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda. Ia bukan hanya sekadar mengagumi, tetapi mencurahkan perhatian mendalam pada budaya Jawa. Dari minat itu lahirlah mahakarya penting berjudul The History of Java, yang terbit pada tahun 1817. Buku ini menjadi salah satu karya paling awal dan komprehensif tentang budaya, sistem sosial, ekonomi, dan religi masyarakat Jawa.
Raffles tak datang dengan ketertarikan tiba-tiba. Ia terinspirasi oleh koleganya, John Leyden, seorang dokter sekaligus orientalis yang memandang budaya Jawa sebagai kebudayaan adiluhung Timur. Leyden mengagumi kedalaman pandangan hidup orang Jawa, yang menurutnya serumit filsafat Yunani. Ia meyakini bahwa budaya Jawa memiliki struktur nilai dan kebijaksanaan yang tinggi—sesuatu yang langka dan berharga.
The History of Java mengulas kebudayaan Jawa dalam berbagai aspek: dari adat istiadat, sistem kepercayaan, geografi, hingga pertanian dan perdagangan. Karya ini bahkan menarik perhatian Karl Marx, tokoh besar dalam sejarah pemikiran dunia. Dalam Das Kapital, Marx sempat menyinggung masyarakat Jawa dalam salah satu catatan kakinya, menunjukkan bahwa budaya ini memiliki kekhasan sosial yang layak dicermati.
Budaya Jawa memang mempesona, karena bukan sekadar sistem kebiasaan atau bahasa. Ia adalah sistem nilai, etika, estetika, dan bahkan filsafat hidup. Karena kelengkapan inilah, antropolog Niels Mulder menyebut budaya Jawa sebagai Javanisme, yaitu suatu “agama” kebudayaan—sebuah pandangan hidup yang menekankan ketenteraman batin, harmoni, keselarasan, serta sikap nrimo (menerima dengan ikhlas), sambil menempatkan individu sebagai bagian dari masyarakat dan masyarakat sebagai bagian dari semesta.
Ekspresi budaya Jawa terlihat dalam berbagai bentuk simbol dan ritual—seperti arsitektur rumah, tempat ibadah, senjata tradisional (keris), hingga upacara-upacara seperti ruwatan, pernikahan, atau kematian. Namun, nilai sejatinya tidak terletak pada simbol atau upacara itu sendiri, melainkan pada makna filosofis yang dikandungnya.
Sungguh disayangkan, jika masyarakat Jawa hari ini semakin tidak mengenal akar budayanya sendiri. Andaipun menjalankan sejumlah tradisi, banyak yang tak lagi memahami nilai dan pesan filosofis di baliknya. Padahal, di tengah dunia yang terus berubah, budaya adalah jangkar yang menjaga jati diri.
Kini saatnya masyarakat Jawa kembali menengok ke dalam, mengenali warisan leluhur, dan merawatnya bukan hanya sebagai kebanggaan masa lalu, tetapi sebagai sumber hikmah dan pegangan hidup di masa depan.