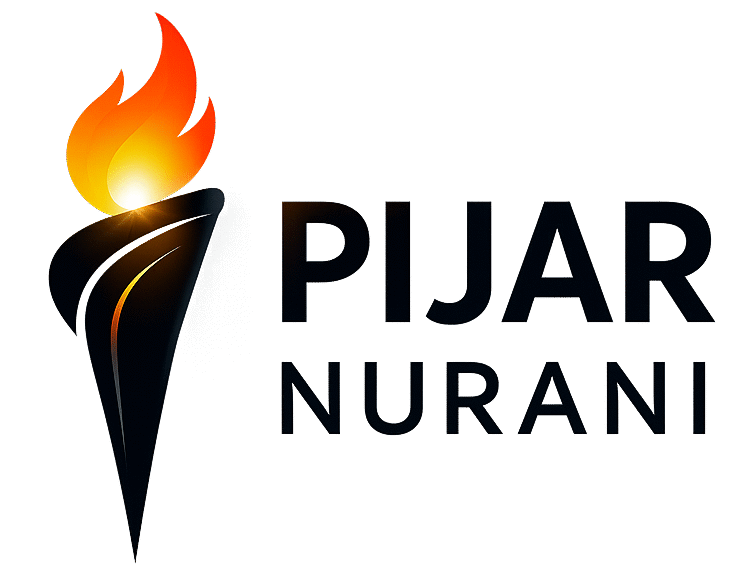Cemburu

CEMBURU
“Aku cemburu padamu, Mas.”
Yulia tiba-tiba mengucapkan kalimat tak biasa pada Pram, suaminya. Wajahnya tampak serius.
Teras rumah, tempat mereka biasa duduk berdua menjelang magrib, terasa berbeda suasananya. Tidak seperti biasanya.
“Cemburu?” tanya Pram, terkejut mendengar ucapan istrinya.
“Iya…”
“Serius?”
“Iya.”
Pram belum paham isi pikiran istrinya. Selama ini ia merasa baik-baik saja. Semua kiprahnya diketahui Yulia. Andaipun ada interaksi dengan perempuan lain, itu sebatas biasa saja, semua terbuka, tak ada yang ditutup-tutupi.
“Aneh. Selama pernikahan sampai sekarang, kamu tak pernah mengucapkan kata itu. Bahkan kita sudah punya dua anak, tak pernah ada rasa cemburu dari dirimu.”
“Justru itu. Kamu tak peka.”
Pram termenung. Rasa bersalah mulai menyelimutinya. Ia berusaha mengingat apa saja yang telah dilakukan. Pikirannya melayang, mencari kemungkinan yang membuat istrinya cemburu.
Benarkah aku tak peka? Benarkah aku selama ini menyakiti hati istriku? begitu suara hati Pram.
Satu per satu wajah perempuan yang pernah ia temui terlintas dalam ingatan. Ia mencoba menimbang, adakah sikapnya yang mungkin dianggap kebablasan di mata istrinya.
“Aku merasa tak menemukan hal yang bisa membuatmu cemburu. Dari dulu aku seperti ini. Tak ada yang berubah.”
“Ada…”
Yulia kukuh dengan pendiriannya. Wajahnya tetap serius. Tatapan matanya membuat Pram bingung dan salah tingkah.
“Sebutkan, perempuan mana yang membuatmu cemburu?” tanya Pram, pasrah layaknya terdakwa di persidangan.
“Bukan perempuan. Tapi kamu…”
Yulia menempelkan telunjuknya ke dada Pram.
“Aku?”
“Iya.”
Pram makin terpojok. Baru kali ini ia melihat istrinya begitu serius.
“Aku cemburu… pada anak-anak yang begitu dekat denganmu,” ucap Yulia, lalu tersenyum sambil memegang pipi suaminya.
“Aku bercanda, sayang. Maaf ya,” kata Yulia merasa bersalah atas sandiwaranya.
Pram langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya lunglai.
“Bercandamu serius, sayang,” ujarnya sambil mencubit hidung mancung Yulia.
“Tapi cemburuku serius, Mas,” balas Yulia sambil memegangi hidungnya.
“Apanya sih yang kamu cemburui, ada-ada saja,” Pram menggeleng. Menurutnya, kecemburuan itu aneh.
“Dengan anak-anak, Mas Pram mesra sekali.”
Yulia memperhatikan, semakin anak-anak tumbuh besar, mereka makin dekat dengan ayahnya. Semua larinya ke Pram. Kalau sudah ngobrol, bercanda, bahkan curhat, mereka lebih lepas pada ayahnya. Yulia merasa tak mampu melakukan itu.
“Ya kan wajar, anak-anak mesra dengan orang tuanya.”
“Tapi denganku tak seperti ke Mas Pram.”
“Itu cuma perasaanmu.”
“Ini soal rasa, Mas. Karena itu aku cemburu.”
“Lalu aku mesti bagaimana?”
Pram tersenyum sambil menggaruk kepala. Ia bingung harus berkata apa.
“Mas Pram sudah benar. Aku hanya ingin curhat saja. Sebenarnya bukan cemburu, lebih tepatnya iri. Seharusnya kedekatan itu pada ibunya.”
Pram terdiam mendengar keluhan istrinya.
“Sembilan bulan anak-anak bersamaku. Sejak bayi, mereka ada dalam pelukanku. Harusnya mereka lebih dekat denganku. Tapi kenyataannya, setelah besar justru lebih dekat dengan ayahnya,” kata Yulia lirih, seperti menyalahkan diri sendiri.
“Tapi aku bersyukur, Mas Pram bisa dekat dengan anak-anak. Tak terbayang kalau aku tak bisa mengambil hati anak-anak, dan Mas Pram juga tak bisa. Kemana larinya anak-anak itu?” sambung Yulia dengan mata berkaca.
“Kamu tak perlu menyalahkan diri sendiri. Bukankah kita saling menutup kekurangan?”
“Harusnya itu tugasku, sebagai seorang ibu yang menampung jiwa anak-anak. Memberikan ketenangan dan keteduhan untuk mereka.”
“Kalau begitu tugasku apa?” tanya Pram polos.
Yulia tersenyum mendengar pertanyaan itu.
“Kamu mengayomi semua, sayang,” jawab Yulia sambil mengusap pipi suaminya.
“Kadang aku merasa bersalah saja,” ucapnya datar.
Pram bangkit dari kursinya, melangkah ke belakang Yulia, lalu meletakkan kedua tangannya di bahu istrinya.
“Dengarkan, ya. Di dunia ini tak ada tugas paling berat melebihi seorang ibu. Mengandung, merawat bayi, membesarkan anak-anak adalah tugas yang tak tergantikan. Tak ada lelaki mana pun yang mampu menggantikan pekerjaan itu. Jika aku berusaha keras membantumu, dengan tenaga dan pikiranku, itu belum seberapa. Kedekatanku dengan anak-anak sebenarnya hanya melengkapi beratnya tugas seorang ibu.”
Pram kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga Yulia. Dengan suara lirih ia berkata, “Tak ada yang salah dengan dirimu, sayang.”
Yulia mendongak, menatap wajah suaminya dengan haru.
“Terima kasih, Mas. Kamu selalu membuatku tenang.”
“Soal kedekatan, mungkin itu hanya soal cara. Kita bisa pikirkan bersama. Karena aku juga ingin anak-anak dekat dengan ibunya.”
Pram kembali duduk.
“Yulia, aku berusaha keras menjaga keluarga ini dengan seluruh diriku. Karena di luar sana, badai kehidupan keras dan dahsyat. Begitu anak melangkah keluar rumah, ia bisa terhempas. Pikiran dan perilakunya bisa tersapu arus yang merusak. Itu sebabnya keluarga harus kuat. Anak-anak harus betah dan nyaman di rumah, sebelum menghadapi dunia luar.”
“Saat ini, sayang, kita sedang bertanding: apakah lingkungan atau keluarga yang lebih kuat memberi pengaruh. Jika lingkungan di luar lebih kuat, kita bisa kehilangan anak-anak kita, meski mereka ada di rumah. Pikiran dan perilaku mereka bisa dibentuk oleh dunia luar, bukan oleh kita.”
Yulia mengangguk haru, mendengar kesungguhan suaminya.
“Lalu kita harus bagaimana?” tanyanya pelan.
“Keluarga ini harus jadi benteng pertahanan kehidupan. Rumah harus jadi tempat terbaik untuk pulang. Karena itu, kita harus kompak dan saling menguatkan.”
Agustus 2023