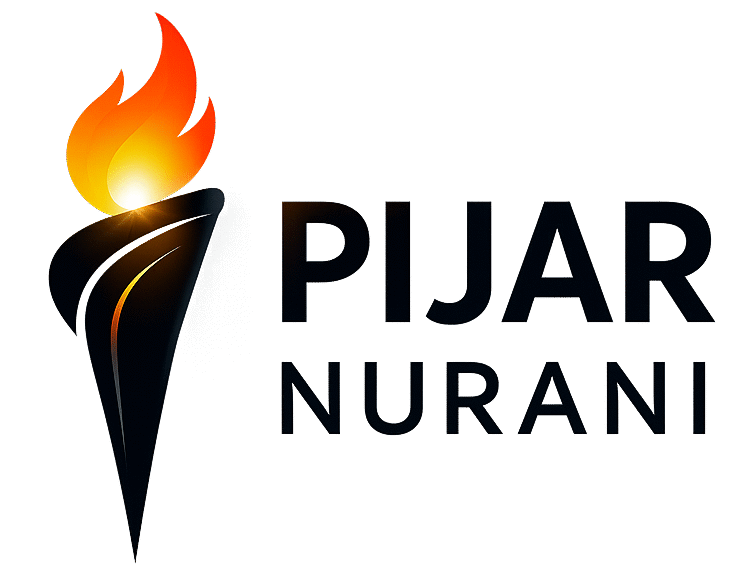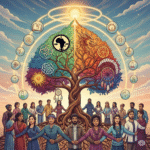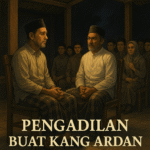Pandanganku atas Iran

Pengenalanku terhadap Iran tidaklah mendalam.
Jika aku memiliki pandangan tentang negara ini, itu bukan karena sejarah panjangnya, kebudayaannya yang kaya, atau bahkan keagamaannya yang kompleks. Sisi yang kutangkap dari Iran lebih pada sosok-sosok elitenya: para pemimpin dan cendekiawannya. Itupun tidak banyak. Karena itu, pandanganku tentang Iran hanyalah serpihan kecil saja. Tidak utuh.
Aku mulai mengenal Iran saat awal masa kuliah, di penghujung tahun 1980-an. Tentu saja, yang pertama kali memikat perhatian adalah revolusi Iran—sebuah peristiwa yang menurutku luar biasa. Sebuah negara yang konon paling kuat di Timur Tengah pada masanya, tumbang oleh gerakan sosial yang dipimpin seorang pemuka agama kharismatik: Ayatollah Khomeini. Sosok Khomeini menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang arogan dan menindas. Sesederhana itu pandanganku.
Setelah itu, kekagumanku tumbuh, terutama kepada generasi muda di sekitar Khomeini yang dipercaya memegang kendali negara. Saat itu, aku mengagumi Menteri Luar Negeri Iran yang masih sangat muda: Ali Akbar Velayati. Usianya baru menginjak tiga puluhan saat menjabat. Aku kagum pada Velayati karena kemudaannya, kepercayaan dirinya, serta keberaniannya mengambil sikap, khususnya dalam menentang imperialisme dan zionisme. Sosok semuda itu telah dipercaya tampil sebagai juru bicara di forum-forum internasional.
Perkenalan selanjutnya datang melalui buku-buku karya para cendekiawan Iran seperti Ali Syariati, Murtadha Mutahhari, dan Muhammad Baqir Al-Sadr. Bagi aktivis era 1980–1990-an, nama-nama itu tentu tak asing. Pemikiran mereka menimbulkan kekaguman tersendiri, karena memadukan ideologi yang kokoh dengan cara berpikir modern yang sangat kontekstual. Para pemikir itu, meski berasal dari lingkungan keagamaan yang konservatif, mampu menawarkan gagasan yang luas dan mutakhir.
Khomeini, begitu pula Khamenei, dalam bayanganku adalah seperti seorang kiai: religius dan spiritual. Namun, pada saat yang sama mereka juga sangat menguasai pemikiran modern. Perpaduan inilah yang membuat kharisma mereka begitu kuat. Bahkan tokoh-tokoh intelektual modern seperti Ali Syariati atau Seyyed Hossein Nasr, jika bertemu Khomeini, bersikap layaknya seorang santri yang mencium tangan kiai, sebagai bentuk penghormatan yang mendalam. Relasi seperti ini terasa asing dalam tradisi kehidupan modern.
Begitulah, pandanganku atas Iran. Bangsa ini mampu merawat tradisi intelektual yang memadukan nilai-nilai tradisional dan modern sekaligus. Islam di sana tidak sekadar menjadi identitas budaya, politik dan ideologi, tapi juga menjadi fondasi berpikir. Kritik-kritik tajam para pemikir Iran terhadap berbagai aliran filsafat modern menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami alam pikir kontemporer.
Gaya pemikiran para cendekiawan Iran—juga para pemimpinnya—membuat bangsa ini berbeda dari negara-negara muslim lainnya. Ideologi yang kuat tidak otomatis menjadi dogma politik semata. Di Iran, ideologi justru berdiri diatasnya intelektualitas yang kokoh. Perlawanan yang mereka bangun bukan hanya terhadap hegemoni politik global seperti imperialisme, zionisme, atau dominasi Amerika Serikat, melainkan juga terhadap dominasi pemikiran modern itu sendiri—melalui kritik yang tajam dan mendalam.
Islam, dalam konteks Iran, benar-benar menjadi kekuatan yang membentuk warna dalam kehidupan sosial, politik, dan intelektual. Maka, ketika Iran kini mampu berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi—termasuk dalam bidang militer—itu tidaklah mengherankan. Pun ketika dari gemuruh perang modern muncul sosok tradisional yang sangat berpengaruh dan memimpin jalannya peperangan, itu juga bukanlah keanehan. Di Iran, kekuatan tradisional dan modern saling bertemu, saling menopang. Sebuah kombinasi yang kadang sulit dipahami, baik oleh dunia Barat maupun oleh sebagian umat Islam sendiri.