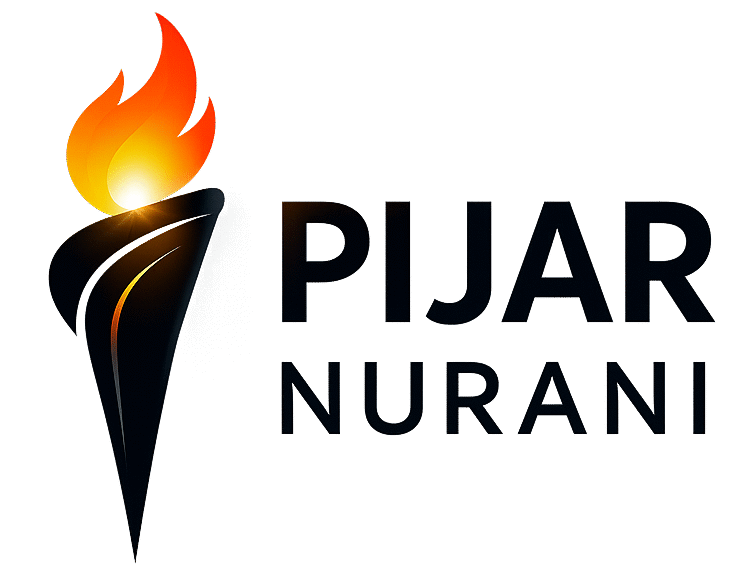Pengadilan Buat Kang Ardan

Malam itu, pendopo rumah Lurah Dharma terasa hening dan sunyi. Semua acara malam itu dibatalkan. Lurah Dharma sedang fokus hanya dengan satu tamunya; Kang Ardan. Sosok lelaki dari Dusun Kunden yang kini sedang dalam sorotan warga.
Di tengah pendopo, sudah duduk Kang Ardan. Wajahnya yang biasa berhias senyum kini terlihat sedikit tegang. Di hadapannya, Lurah Dharma duduk dengan sorot mata tajam tapi tenang, mengenakan baju koko putih dan sarung bergaris halus. Di sisi pendopo, lima lelaki dan dua perempuan—warga Dusun Kunden—datang diam-diam menyusul Kang Ardan. Pak Lurah Dharma tak bisa mencegah dan membiarkan mereka duduk di kursi tamu.
Tiara, istri Lurah Dharma, ikut hadir. Ia duduk mendampingi dua ibu-ibu yang tak berhenti menggenggam tangannya. Satu di antaranya, Bu Rini, sudah sejak sore gelisah. Kabar berseliweran, Kang Ardan akan meninggalkan kampung demi ketenangan warga dusun. “Kalau Kang Ardan pergi, Bu Lurah, kami ini seperti kehilangan tiang rumah,” bisiknya pada Tiara, Isteri Lurah Dharma.
Kang Ardan memang bukan penduduk asli. Ia datang ke Dusun Kunden empat tahun lalu. Tak ada yang tahu pasti asalnya. Tapi sejak kehadirannya, masjid dusun yang dulunya sepi kini ramai jamaah. Anak-anak saban sore belajar mengaji. Remaja dusun banyak menyelenggarakan kegiatan yang berpusat di Masjid. Bahkan para bapak sering kumpulan yang tempatnya di masjid.
Tak hanya masjid, pertanian warga pun bergeliat. Kang Ardan mengajarkan cara bertani yang benar, mendorong warga menanam sayur di pekarangan, mengenalkan tanaman obat keluarga, dan menghidupkan kembali kebun-kebun kosong.
Kang Ardan juga menghidupkan tradisi lama yang hampir hilang, menjadikannya semacam pesta budaya yang meriah. Sejak ada Kang Ardan Dusun Kundem menjadi semarak dan hidup.
Tapi ketenangan itu terusik, sajak dua tokoh baru, Ustadz Maliki dan Ustadz Pandowo, kembali dari kota. Mereka adalah warga dusun asli yang belajar agama di kota. Ilmu mereka dalam, ceramanya memukau, dalil mereka fasih. Wibawa mereka cepat menjalar.
Tak lama setelah kembali.ke desa, mereka segera mendapat sambutan. Mereka mulai berceramah di dusun-dusun, dari mushola ke mushola, dari masjid ke masjid, bahkan ceramahnya hingga desa sebelah. Jamaahnya juga makin ramai.
Dan salah satu yang kini ramai dibicarakan adalah kritik mereka pada gerakan Kang Ardan di Dusun Kunden.
Dengan alasan bahwa cara beragama yang dibawa Kang Ardan tidak sesuai ajaran yang benar. keduanya menyebut bahwa pengaruh Kang Ardan “membawa bahaya tersembunyi.” Bahwa aktivitasnya yang meriah di masjid bisa menjerumuskan warga dalam ibadah tanpa ilmu, mencampurkan agama dan budaya. Kritikan itu cepat menyebar. Di warung kopi, di beranda masjid, bahkan di tempat warga biasa berkumpul. Isu itu membesar.
Kang Ardan sendiri tidak pernah membalas berbagai suara yang mengarah kedirinya. Ia memilih diam dan mengajak warga melakukan aktifitas seperti.biasa. Kang Ardan tahu diri, Ia tak punya kemampuan agama yang cukup. Pun tak punya. Kemampuan berdebat. Ia tahu batas dirinya.
Lurah Dharma merasa suasana di desanya tak sehat. Warganya terbelah antara yang mendukung dan yang turut mengkritik Kang Ardan.
Itulah sebabnya malam ini Kang Ardan duduk di pendopo. Ia datang karena dipanggil Pak Lurah.
Pak Lurah Dharma membuka pembicaraan. Suaranya pelan, dalam, seperti menimba dari dasar sumur.
“Kang Ardan, maaf nih,” kata Lurah Dharma tenang dan perlahan. “Sebagai Kepala Desa saya tak paham mengapa situasi seperti ini bisa terjadi. Sebelum marak syiar agama, desa ini baik-baik saja, guyub-guyub saja. Mengapa sekarang menjadi panas begini, ya? Apa pandangan Kang Ardan?”
Pertanyaan Lurah Dharma membuat wajah Kang Ardan menunduk. Beberapa saat kemudian ia mendongakkan wajahnya menatap Lurah Dharma yang terlihat ada.kerisauan yang mendalam.
Warga yang ikut duduk melingkar, termasuk Tiara Isteri Pak Lurah, terlihat sedikit tegang menanti jawaban Kang Ardan.
“Saya juga tak paham, Pak Lurah. Selama ini saya juga merasa baik-baik saja” jawab Kang Ardan.
Lurah Dharma melanjutkan lagi pertanyaan, “Apa jawaban Kang Ardan terhadap semua kritik yang ditujukan pada anda?”
Kang Ardan diam sejenak. Sebuah pertanyaan yang baginya sulit dijawab.
“Pak Lurah, ” kata Kang Ardan setelah menarik nafas panjang. “Saya ini tak punya pengetahuan apa-apa tentang agama. Karena itu saya tak bisa menjawab apa-apa. Selama ini saya hanya mengajak mereka sholat di masjid, menemani mereka melakukan kegiatan dan menemani warga bertanam. Hanya itu yang saya lakukan. Saya tak mengajarkan apa-apa karena memang saya tak punya ilmunya”
Tiba-tiba Pak Sarpin menyela, “Saya juga tak paham Pak Lurah, orang sebaik Kang Ardan kok dibilang sesat, apanya.yang sesat”
Dari bangkunya, Bu Rini tak sabar bicara. Sambil tangannya masih memegang jari Tiara, ia berujar, “Pak Lurah, sejak ada Kang Ardan, dusun kami makin guyub, kompak dan maju. Anak-anak dan pemuda menjadi terarah, lahan dan halaman rumah kami menghasilkan. Saya juga bingung, apa yang salah dari Kang Ardan”
Lurah Dharma hanya diam dan mendengar seksama suara warga yang ikut bicara. Ia merasa terharu begitu besar perhatian dan pembelaan warga pada Kang Ardan meski ia sedikitpun tak minta dibela.
Ketika Lurah Dharma hendak bicara, Pak Kardi salah satu sesepuh dusun yang sejak tadi diam angkat bicara, “Mungkin Nak Ardan ini disalahkan karena dia menghidupkan upacara adat yang selama ini mulai redup. Mungkin Nak Ardan dianggap mencampuradukkan agama dengan acara adat. Tapi apa salahnya? Warga merasa bahagia dengan kegiatan yang sudah turun temurun?”
Setelah mendengar semua pandangan warga, Lurah Dharma bertanya lagi pada Kang Ardan, “Apa sikap anda selanjutnya, Kang Ardan? Apa yang akan anda sampaikan untuk menyelesaikan masalah ini?”
Kang Ardan menatap dalam-dalam wajah Pak Lurah dan memutarkan pandangannya kepada semua warga yang hadir di pendopo. Seperti ada perasaan dihatinya yang berat untuk dikatakan.
“Saya merasa bersalah, Pak Lurah. Saya sudah mengganggu.ketenangan desa ini,” ucap Kang Ardan dengan nada yang berat, “Saya bukan siapa-siapa. Tidak punya ilmu. Saya hanya mencoba membantu warga, menemani mereka ke masjid, ke kebun. Tapi sekarang, saya malah jadi sumber perpecahan. Itu sebabnya… ijinkan saya pergi, demi kekompakan desa ini dan kecintaan saya pada dusun Kunden.”
Mendengar ucapan Kang Ardan, sontak warga yang ikut disitu sedikit gaduh. Kekhawatiran yang selama ini, Kang Ardan memilih pergi, menjadi kenyataan. Sebagian bapak-bapak berusaha mencegah. Sementara Bu Rini hanya bisa bicara dengan air matanya.
Pak Lurah membiarkan drama kegaduhan itu terjadi. Kemudian ia meminta semua duduk dengan tenang. “Bapak-Ibu, jika masih ingin duduk di pendopo bersama kami, saya mohon tenang ya. Kita sedang cari solusi terbaik.
Suasana kembali hening. Semua duduk dengan raut wajah tegang menanti apa kata Lurah Dharma.
“Kang Ardan,” ujar Lurah Dharma, “Anda tahu sendiri betapa cintanya warga Dusun Kunden pada Anda. Saya hanya ingin tahu satu hal saja. Mengapa anda bertahan selama ini di Pundan? Mengapa anda melakukan ini semua?”
Kang Ardan menatap wajah Lurah Dharma. Suaranya kini lebih tenang.
“Saya datang ke desa ini sesungguhnya hanya untuk mencari ketenangan, Pak Lurah. Saya punya masalah yang tak mungkin saya ceritakan di sini. Ini pelarian.”
“Di Dusun Kunden ini,” sambung Kang Ardan, “… ketenangan itu saya dapatkan. Lebih dari itu, saya mendapatkan cinta yang berlimpah dari warga. Saya merasa bahagia bersama mereka, Pak Lurah”
Kang Ardan bicara dengan hati dan kata-kata yang terbata-bata. Matanya tampak basah.
“Soal agama, saya benar-benar tak punya ilmu. Seseorang pernah berkata pada saya, agama itu intinya amal. Dan sebaik-baik orang itu yang memberi manfaat bagi orang lain. Hanya itu pengetahuan saya, Pak Lurah, dan hanya itu ilmu agama yang saya praktekkan. Jangan tuntut saya bicara lebih dari itu, saya tak punya”
Suasa Hening. Tak ada lagi sahutan kata-kata.
Lurah Dharma terdiam sejenak setelah Kang Ardan selesai bicara. Ia menatap Kang Ardan lama, lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang ada di pendopo.
“Semua kalian tenang, dengarkan baik-baik” kata Lurah Dharma dengan suara berat dan penuh wibawa. “Jika saya ditanya, siapa.yang pantas menjadi lurah di desa ini, saya akan katakan Kang Ardan orangnya”
Semua terperangah dengan ucapan Lurah Dharma, termasuk Kang Ardan. Bu Rini makin kencang menggenggam tangan Tiara seperti ada getaran jiwa yang ikut mengalir di dada secara tiba-tiba.
“Andai jabatan Lurah bisa kulepas dan kuberikan pada orang lain, hari ini juga akan saya berikan pada Kang Ardan, dan saya siap berdiri dibelakangnya, beserta isteri dan seluruh yang saya miliki untuk desa ini. Tapi itu tak mungkin. Itu tak bisa dan saya tahu bukan itu yang dimaui kang Ardan.”
“Kali ini,” sambung Lurah Dharma, “saya mohon, anda tetap tinggal di Dusun Kunden bersama cinta anda pada warga dan cinta warga anda. Mari bantu saya membangun desa ini. Bantu saya bekerja dengan cinta dan menyalakan agama dikehidupan nyata”
“Saya tahu, ” ujar Lurah Dharma lagi, “Anda tidak butuh posisi. Tapi saya ingin anda tetap jadi cahaya. Perkara Ustadz Maliki dan Pandowo, itu urusan saya. Mereka saudara kita. Akan saya bawa mereka bicara dari hati ke hati. Tapi jangan biarkan kebaikan tumbang hanya karena berbeda cara.”
Kang Ardan berdiri perlahan. Ia membungkuk, dalam, seperti takzim kepada seluruh semesta. “Saya akan tetap tinggal, Pak lurah, jika saya diizinkan.”
Lurah Dharma ikut berdiri melangkah pelan dan memeluk Kang Ardan. Pelukan yang berat, dalam, dan penuh penghargaan.
Malam itu, pendopo yang semula terasa seperti ruang sidang, justru berubah menjadi ruang maaf, ruang pengakuan, dan ruang cinta. Ketika semua orang paham, bahwa yang dibutuhkan bukan siapa yang paling fasih, tapi siapa yang paling tulus memberi manfaat.
Tiara menatap suaminya dengan mata yang berbinar. Ia tahu, suaminya bukan hanya kepala desa, tapi pemimpin yang mampu melihat cahaya di balik diam. Dan Kang Ardan, pemuda yang tak bicara banyak, malam itu membuktikan satu hal: bahwa cinta kepada desa, kepada manusia, dan kepada kebaikan tak selalu memakai mikrofon atau dalil. Kadang cukup dengan tangan yang menggarap tanah, dan hati yang tak pernah letih melayani.
Lihat insight dan iklan