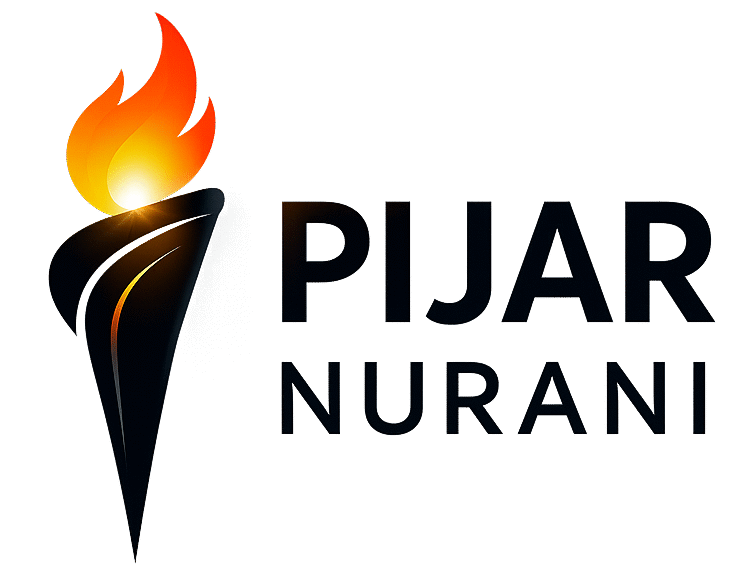Tentang Cak Nur (1)

Bagiku, itu sesuatu. Ketemu tokoh yang kukagumi dan dikagumi banyak orang karena kepintarannya. Apalagi aku orang kampung yang memandang sosok itu seperti jauh tak tersentuh.
Satu kesempatan aku bisa bertemu. Kami bisa berbincang panjang lebar. Pernah juga aku makan satu meja, jalan berdua, bahkan sesekali kita berdebat.
Kesanku saat pertama bertemu, Ia amat terbuka, ramah dan rendah hati. Aku merasa dibuat nyaman dihadapannya. Menurutku, pada yang muda, Ia sangat respek dan mau mendengar.
Soal akademis jangan diragukan. Posisinya sudah menjulang di puncak. Ia seorang profesor. Bahkan saking mumpuninya, ia dijuluki sang begawan karena cakrawala ilmunya amat luas.
Namanya Nurcholish Madjid. Aku memanggilnya Cak Nur. Satu panggilan akrab yang menurutku cukup egaliter dan ‘mesra’. Ia tak keberatan dengan sebutan itu. Ia juga tak risau atau bahkan tak peduli dengan segala macam sebutan predikat akademik.
Menurutku Ia seorang akademis sejati. Ia amat produktif menulis. Pun menjadi pembicara di berbagai forum ilmiah. Buku-buku karyanya juga mewarnai jagad pustaka nasional.
Pengalamanku saat berbincang dengannya, segala yang terucap darinya adalah khasanah ilmu. Ia tak hanya kuasai teks, tapi juga menempatkan konteks pada isu yang sedang dibahas. Pendeknya, soal keilmuan, utamanya dibidang keagamaan, menurutku ia sudah pada level pawang.
Pada momen-momen kritis kenegaraan, Ia selalu tampil ambil peran memberi kontribusi pemikiran. Cak Nur juga tak segan mengambil sikap berseberangan dengan rezim berkuasa jika dinilainya melakukan penyimpangan. Kehadirannya di momen krisis itu, ia seperti juru bicara publik terhadap kekuasaan. Ia sosok akademis, tapi juga sosok yang tegas dan berani dibalik sikap santun dan lembutnya.
Saat ini Ia sudah tak ada. Yang tersisa dari sang profesor itu hanya kerinduan tentang untaian pemikiran yang mencerahkan, tesis-tesis segar dan diskursus yang mencerdaskan, serta kehadirannya di saat krisis.
Sekarang, profesor makin banyak. Bahkan gelar itu diburu dengan segala cara. Kalau perlu dengan cara curang. Ada prestise dibalik gelar itu. Ada kegagahan dan kebesaran. Sebagian senang dan bangga disebut gelar itu bersamaan dengan namanya. Bahkan ada yang tersinggung jika gelar itu tak disebut.
Gelar itu kini, tak selalu berbanding lurus dengan mutu pikiran. Dari gelar yang makin banyak itu, tak makin banyak lahir gagasan segar, tesis, diskursus dll. Profesor tak lagi identik dengan produktifitas karya akademik. Keberadaan profesor justru memasuki wilayah birokrasi atau jabatan yang sesungguhnya bukan habitatnya. Gelar profesor lebih terasa nuansa feodal dari pada simbol kecermelangan pikiran.
Akhirnya, Alfatehah buatmu Cak. Maafkan jika aku selalu memanggilmu Cak, meski panggilan Prof amat pantas buatmu. Terimakasih atas semua pelajaran dan keteladanmu buat bangsa dan negeri ini. Semoga mendapat tempat terbaik disisiNya.