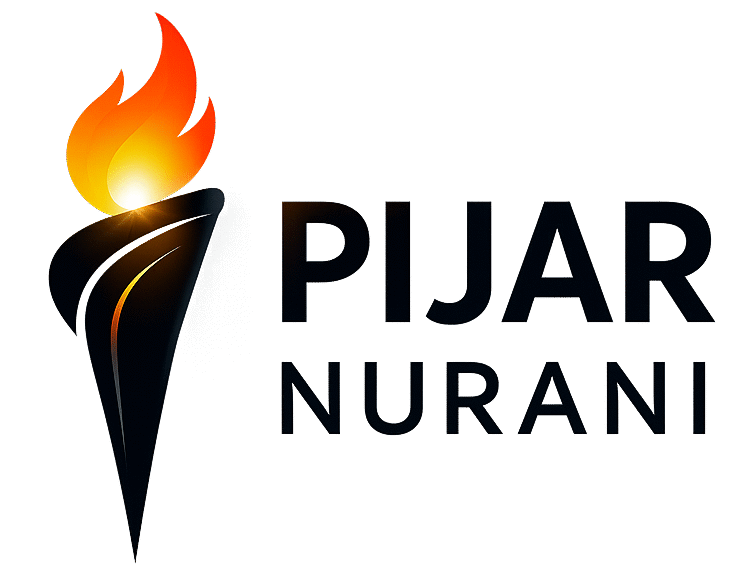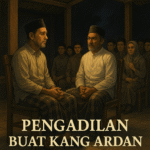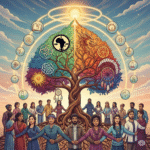Wajah Kemiskinan

Wajah Kemiskinan
Satu pengalaman mengesankan adalah ketika suatu saat saya diundang oleh seorang kawan yang memiliki objek wisata alam di Bali. Saya diminta mampir dan menginap semalam di tempat itu.
Objek wisata tersebut sepintas tampak sederhana saja. Bertempat di sebidang lahan perkampungan yang agak jauh dari permukiman warga, di lokasi itu terdapat lapangan berumput tak terlalu luas yang di sampingnya berderet aneka kemah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kemah-kemah tersebut ditata apik dengan layout kamar layaknya hotel. Di depannya ada taman bunga dan jalan penghubung antar-kemah dari bebatuan yang disusun rapi.
Di sekeliling lokasi wisata itu tumbuh semak-semak dan rerimbunan pepohonan yang tinggi menjulang. Dari sisi panorama, tidak ada yang tampak terlalu istimewa. Kesan awal yang muncul bukanlah pemandangan indah, melainkan nuansa berkemah di sebuah desa yang masih natural.
Pengelola memang tidak menawarkan keindahan alam layaknya pesona wisata Bali. Daya tariknya lebih pada tempat istirahat santai dengan fasilitas outbound dan hiburan seni tradisional oleh warga setempat.
Mungkin sudah biasa bagi wisatawan ke Bali untuk menikmati panorama alam dan tinggal di hotel. Namun, menginap di perkemahan dengan nuansa alam pedesaan yang natural serta hiburan seni tradisional adalah “sesuatu” yang unik. Terbukti, wisatawan silih berganti datang dan menginap di situ, meski harganya relatif mahal—nyaris setara dengan tarif hotel berbintang.
Kesan menarik lain saat saya tinggal di sana adalah kesempatan bergaul dan berbincang dengan warga. Sudah menjadi kebiasaan kawan saya, setiap kali koleganya datang, selalu diadakan acara “sarasehan kecil” bersama warga. Konon katanya, ini untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Para tamu diminta berbicara apa saja yang bisa menambah pengetahuan warga.
Malam itu, saya berbaur dengan warga. Ada sekitar 10 hingga 15 orang hadir, mulai dari warga biasa hingga tokoh masyarakat. Saya sendiri tidak tahu akan membicarakan apa. Mungkin karena suasananya yang guyub, ceria, dan penuh canda, rasa grogi saya sedikit berkurang.
Dari obrolan santai itu, akhirnya saya menemukan “pintu” untuk mulai bicara. Rupanya, menurut data statistik, desa tempat lokasi wisata itu berada termasuk salah satu yang termiskin. Sudah lama predikat “termiskin” itu melekat, dan warga tampaknya tidak terlalu peduli.
Ketika diminta berbicara, ide mengalir begitu saja. Pertama, saya sampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada masyarakat Bali. Di tengah arus besar modernisasi dan fakta bahwa Bali adalah salah satu pusat wisata dunia, kebudayaan Bali tetap tegak berdiri. Ketika banyak kebudayaan tradisional runtuh, masyarakat Bali masih setia menggenggam nilai dan cita rasa budayanya. Wisatawan dengan segala kebudayaannya justru menyesuaikan diri dengan tradisi lokal, bukan sebaliknya.
Kedua, kehidupan modern bukan hanya membawa nilai-nilai budaya, tetapi juga cara berpikir, termasuk dalam membuat ukuran-ukuran kehidupan. Kemiskinan adalah salah satunya, yang dipaksa menjadi ukuran. Materialisme modern mengukur kemiskinan dari kepemilikan materi. Dari situ, muncullah angka-angka kemiskinan.
Kata “termiskin” boleh dibilang menggambarkan bentuk kekurangan atau krisis kepemilikan. Di dalamnya terselip potret nestapa, dan mungkin saja ketidakbahagiaan.
Namun, sejak awal bertemu warga di forum itu, saya tidak melihat gurat wajah kesedihan. Canda tawa sejak awal pertemuan menggambarkan cita rasa kegembiraan—kalau tidak boleh dibilang kebahagiaan. Rasanya, predikat “termiskin” tidaklah menggambarkan suasana hati dan batin warga. Saya berani menjamin, bila kegembiraan dan kebahagiaan bisa ditukar dengan uang, angka kemiskinan akan berubah drastis. Desa ini bahkan bisa keluar dari status “miskin” dan menjadi desa makmur sejahtera.
Sayangnya, kita belum mampu membuat ukuran-ukuran kita sendiri tentang kehidupan. Kita masih belum merdeka, bahkan untuk urusan satu ini: kemiskinan.
Juni 2021