Ukuran Keberagamaan
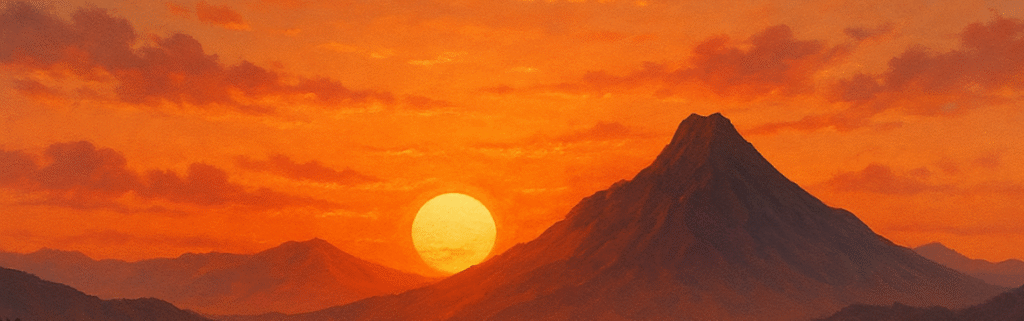
Keberagamaan tentu bukan hal yang statis. Ia senantiasa mengalami dinamika, perubahan, dan bahkan sering kali diperdebatkan bentuk dan ukurannya. Dalam dimensi peribadahan, ukuran keberagamaan bisa diukur dengan standar fikih: ada syarat dan rukun, ada yang sah dan batal. Ini adalah ukuran yang teknis dan bisa ditelusuri secara jelas melalui nash dan praktik ibadah.
Pada sisi lain, kesemarakan keberagamaan juga bisa dilihat dari geliat dakwah dan syiar. Majelis taklim ramai, masjid penuh jamaah, ceramah tersebar di televisi dan media sosial. Pembangunan masjid juga berlangsung di mana-mana, bahkan Indonesia disebut sebagai negeri dengan masjid terbanyak di dunia. Indeks religiusitas masyarakat juga tergolong tinggi. Semua ini adalah ukuran-ukuran formal dan kuantitatif dari keberagamaan yang patut disyukuri.
Namun, semua ukuran itu belum tentu mencerminkan substansi keberagamaan yang sebenarnya. Ada ukuran lain yang jauh lebih mendasar, yang lebih menentukan apakah keberagamaan itu benar-benar hadir secara utuh dalam kehidupan manusia. Ukuran itu adalah dampak sosial.
Dalam Surat Al-Ma’un, Allah secara terang menyebut siapa pendusta agama: adalah mereka yang menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan orang miskin. Dua kelompok ini—yatim dan miskin—adalah simbol dari kaum papa, dhuafa, yang menjadi indikator kepedulian sosial. Maka, keberagamaan yang tidak melahirkan kepedulian sosial, adalah keberagamaan yang dusta. Sebuah pesan yang jelas dan tegas.
Tanpa mengurangi pentingnya ibadah ritual yang bersifat vertikal, surat Al-Ma’un menunjukkan betapa radikal dan progresifnya pandangan Al-Qur’an tentang ukuran keberagamaan. Ibadah tidak hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana kehadiran agama menjawab problem kemanusiaan.
Ukuran keberagamaan ini juga ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Hadis ini dengan tegas mengukur kualitas keberagamaan dari kemanfaatan sosialnya. Apapun mazhab, ormas, aliran, atau gaya keberagamaan seseorang, hanya akan bermakna jika membawa manfaat nyata bagi orang lain.
Bahkan lebih ekstrem lagi, ada hadis tentang seorang pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing kehausan. Ini kisah yang menggetarkan. Bukan karena pelacur masuk surga, tapi karena tolok ukur keberagamaan dalam kisah itu adalah kepedulian terhadap makhluk lemah, bahkan sekedar binatang. Dalam hal ini, anjing menjadi simbol semua makhluk hidup non-manusia—alam, satwa, dan lingkungan secara umum.
Dengan bahasa yang lebih lugas: keberagamaan, seberapa pun maraknya, adalah dusta jika di tengah masyarakat masih banyak orang kelaparan, stunting, anak-anak kurang gizi, atau kemiskinan merajalela. Keberagamaan adalah dusta jika binatang-binatang kehilangan habitat, jika alam rusak, hutan digunduli, sungai tercemar, udara tak layak dihirup. Bahkan, puncak kedustaan keberagamaan adalah ketika umat manusia justru menyumbang pada pemanasan global yang mengancam kehidupan di bumi.
Semua itu menunjukkan bahwa keberagamaan seringkali gagal memberi dampak nyata bagi lingkungan dan kemanusiaan. Padahal, spirit dasar agama adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Jika kehadiran agama tidak mampu membawa perubahan pada nasib manusia dan alam sekitar, maka sangat mungkin ada yang salah dalam cara kita memahami dan mengamalkan agama.
Secara faktual, banyak indikator sosial dan ekologi justru menunjukkan kemunduran dan krisis. Ini seharusnya menjadi peringatan bahwa ada yang keliru dalam keberagamaan kita. Perlu ada cara pandang baru yang lebih progresif, reflektif, dan berdampak nyata. Sebab jika tidak dilakukan perubahan, semua kemegahan dan kesemarakan keberagamaan itu hanyalah dusta.
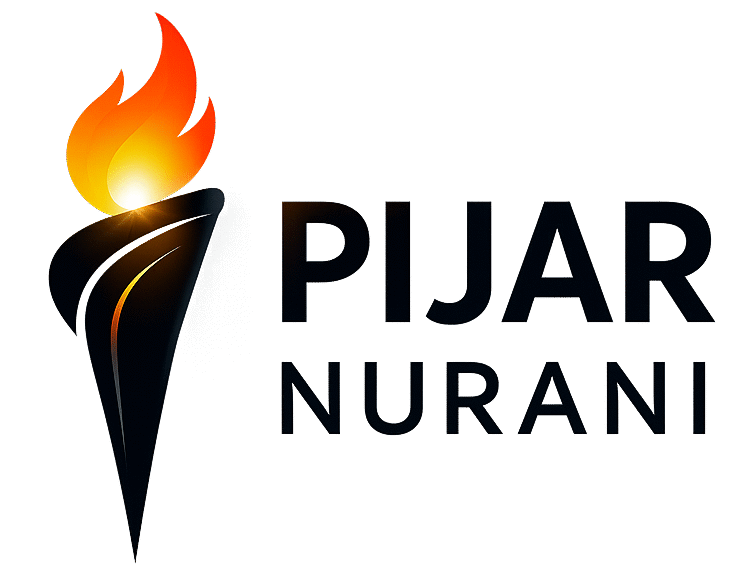
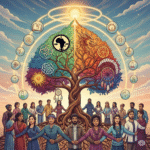
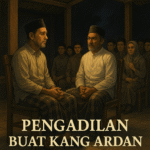

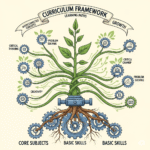


Test