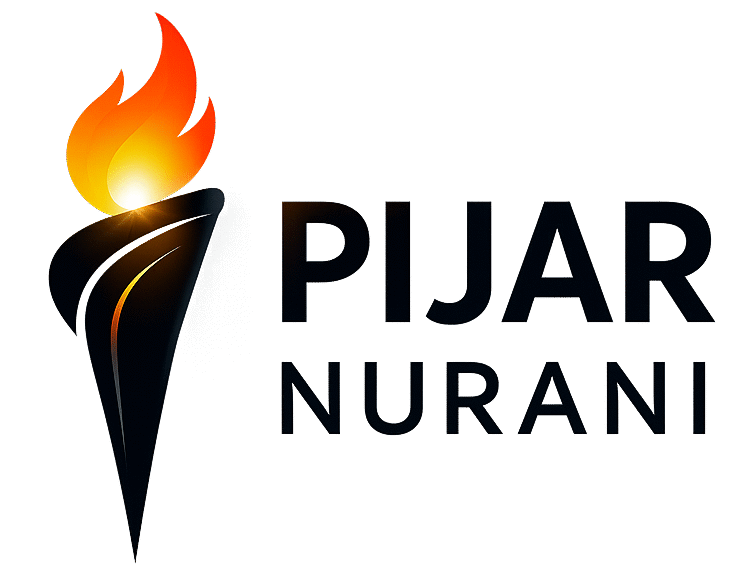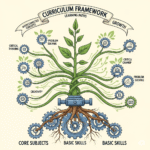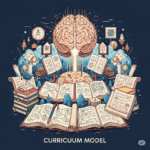Gemuknya Kurikulum Kita

Kurikulum pendidikan kita amat gemuk—terlampau gemuk, bahkan. Sejak jenjang sekolah dasar, berbagai disiplin ilmu dijejalkan ke dalamnya: sains, bahasa, ideologi, agama, hingga muatan lokal. Semuanya dikemas dalam satuan pelajaran yang berdiri sendiri, seolah-olah setiap bidang adalah dunia yang terpisah dan harus dihafalkan secara utuh. Tidak heran jika tas siswa kita kian berat, baik secara harfiah maupun mental.
Kurikulum yang terlalu padat ini mencerminkan satu hal: ambisi yang kelewat batas dari sistem pendidikan kita. Ambisi untuk mencetak “manusia sempurna” versi negara, yang menguasai banyak hal sejak dini. Namun dalam praktiknya, justru menghasilkan anak-anak yang kelelahan, kehilangan rasa ingin tahu, dan terjebak dalam rutinitas belajar yang kaku dan membosankan.
Dalam kurikulum yang gemuk ini, tidak ada ruang untuk bernapas, apalagi tumbuh. Setiap jam pelajaran adalah kewajiban baru, setiap mata pelajaran adalah daftar panjang kompetensi yang harus dikuasai. Sekolah tak lagi menjadi ruang untuk menemukan makna, melainkan menjadi tempat untuk memenuhi target. Apa yang terjadi? Anak-anak duduk diam sepanjang hari, mendengar guru berceramah, menghafal materi, dan menyelesaikan soal. Pendidikan kehilangan jiwanya.
Padahal, pada usia sekolah dasar, anak-anak lebih membutuhkan pengalaman belajar yang menyenangkan, kreatif, dan eksploratif. Mereka butuh bermain, bergerak, bertanya, dan bereksperimen. Mereka bukan keranjang kosong yang siap diisi berbagai macam pengetahuan, melainkan tunas kehidupan yang sedang mencari cahaya. Tapi apa yang mereka dapatkan? Silabus yang panjang, materi yang berat, dan tekanan nilai yang mencekik.
Lebih memprihatinkan lagi, kurikulum gemuk ini tidak pernah bertanya: untuk apa semua ini? Apakah semua pengetahuan itu sungguh relevan bagi kehidupan anak-anak? Apakah kompetensi yang ditargetkan betul-betul akan membentuk karakter, memperkuat empati, atau menumbuhkan kreativitas mereka?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang semestinya menjadi pangkal reformasi kurikulum. Kita perlu berani mengevaluasi: apakah semua tuntutan ini memang harus masuk kurikulum? Apakah semuanya harus diajarkan dalam bentuk satuan pelajaran yang kaku? Tidak bisakah berbagai bidang itu diintegrasikan dalam model pembelajaran yang lebih sederhana, fleksibel, dan menggairahkan?
Fakta bahwa sistem home schooling seperti yang dilakukan Kak Seto mampu mencapai hasil belajar yang setara, bahkan lebih baik, dengan waktu belajar hanya tiga jam sehari, tiga hari dalam seminggu, adalah ironi tersendiri. Di sana, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan, kontekstual, dan personal. Bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membangkitkan minat dan daya hidup anak. Ini membuktikan bahwa yang kita perlukan bukanlah kuantitas jam belajar atau tumpukan mata pelajaran, melainkan kualitas interaksi dan relevansi materi.
Sudah saatnya kurikulum kita direstrukturisasi dari akarnya. Tidak cukup sekadar direvisi secara administratif. Kita butuh perubahan paradigma: dari kurikulum yang menjejalkan ke kurikulum yang membimbing. Dari kurikulum yang membebani ke kurikulum yang membebaskan. Pendidikan seharusnya menjadi jalan menuju kemerdekaan berpikir, bukan lorong sempit yang membuat anak kehilangan jati dirinya sejak dini.