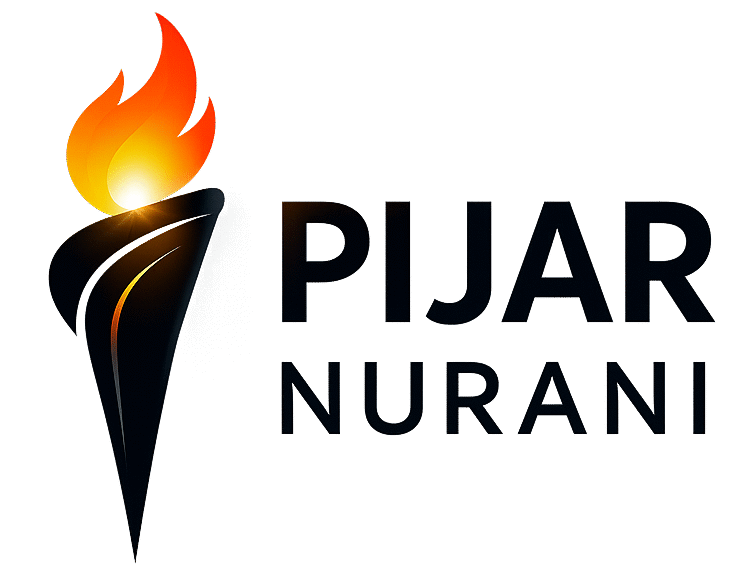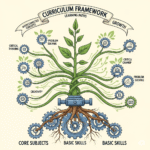Kepalsuan

Kepalsuan
Barang palsu adalah hal biasa di sekitar kita. Kepalsuan bahkan memiliki gradasi. Istilah populernya: KW—ada KW 1, KW 2, dan seterusnya. Intinya, barang itu tidak asli. Namun kondisi ini sudah dianggap lumrah. Barang KW disampaikan dengan kejujuran: pembeli tahu bahwa yang dibelinya bukan barang ori. Dalam hal ini, tidak ada kebohongan.
Penipuan terjadi ketika barang palsu dibilang asli. Di sinilah letak persoalan. Perilaku menipu seperti ini yang biasanya memicu kemarahan.
Dalam iklim kewarasan, berbohong adalah aib. Orang waras akan berat melakukannya. Kalaupun harus berbohong, biasanya disertai seribu dalih.
Kebohongan harus ditutup dengan kebohongan lain. Itu pun biasanya dilakukan diam-diam, bukan terang-terangan. Sebab, kebohongan menyangkut kredibilitas, harga diri, dan pada akhirnya: kepercayaan.
Hanya orang bebal, atau yang mengalami gangguan jiwa, yang berani berbohong secara terbuka—apalagi jika dilakukan berulang kali. Bila itu terjadi, barangkali ada syaraf yang putus, atau urat malu yang terkilir.
Namun kini, bohong atau tidak bohong, tak lagi penting. Orang bisa dan biasa berbohong tanpa rasa canggung. Bohong nyaris tanpa konsekuensi. Kebohongan hadir di dunia maya sebagai hoaks, dan di dunia nyata sebagai bagian dari laku sehari-hari. Pelakunya bukan hanya orang biasa tapi juga pejabat. Nilai-nilai kejujuran bukan lagi menjadi standar moral.
Di panggung politik dan pemerintahan, kebohongan sudah menjadi kelaziman. Ingkar janji politik itu hal biasa. Melanggar sumpah jabatan tak lagi menyentuh soal martabat dan harga diri.
Dalam skala lebih luas, kepalsuan-kepalsuan lain juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernagara. Semisal, katanya kedaulatan di tangan rakyat. Pernyataan itu lebih banyak bohongnya. Rakyat dalam praktek tak berdaulat. Keberadaannya hanya penonton atau berposisi sebagai obyek.
Disebutkan tugas negara melindungi segenap bangsa, nyatanya anak-anak bangsa sering justru tidak aman dihadapan negara. Katanya negara memajukan kesejahteraan umum, tapi kemakmuran itu berkumpul pada sekelompok orang. Disebutkan tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, pada prakteknya mereka yang sadar dan kritis sering mendapatkan tekanan dan ancaman. Dari pemikiran sederhana tersebut bahwa jika saat ini ada yang disebut negara, itu pasti lebih banyak unsur kepalsuannya.
Maka, jika kebohongan telah menjadi warna negeri, maka soal ijazah palsu hanya perkara kecil saja, diantara banyak kepalsuan lain. Tak ada yang mengejutkan.
Tetapi proses hukum biarlah terus berjalan. Mereka yang berselisih teruslah berjuang. Jika beruntung, mungkin bangsa ini masih bisa mendapatkan sisa-sisa nilai luhur yang cukup berharga: kejujuran.