Atheisme dan Korupsi

Atheisme, Korupsi, dan Zaman Ganjil
Ketika ditanya soal ateisme seseorang, saya bilang: saya tak mengerti. Jangankan ateisnya, keberagamaan dan keimanan seseorang pun saya tidak sepenuhnya paham. Saya baru bisa menjawab dengan pasti jika ucapan seseorang sesuai dengan suara hatinya. Sayangnya, saya tak pernah tahu, apalagi mendengar, isi hati seseorang—maka saya tak bisa ‘menghukumi’.
Mungkin saja seseorang secara radikal dan intelektual menyatakan diri sebagai ateis, tapi di dalam hatinya percaya pada Tuhan dan dalam praktiknya menjalankan banyak perintah-Nya. Kata-kata dan ide tak selalu menjelaskan isi hati.
Pun mereka yang mendeklarasikan diri sebagai orang beriman, belum tentu hatinya benar-benar percaya dan patuh pada ajaran Tuhan. Bisa jadi, dalam diam, Tuhan dianggap tak ada.
Saya hanya bisa menghormati apa pun sikap dan cara pandang seseorang. Bagi saya, wilayah keyakinan adalah ranah privat yang tak tersentuh. Dalam konteks sosial, yang penting adalah bisa srawung—bergaul dengan sesama, saling menghormati, dan saling memberi manfaat. Itu sudah lebih dari cukup.
Wacana ateisme belakangan muncul karena kata itu sering disebut. Ada yang mengangkat isu ini dalam konteks ideologi, ada pula yang membahasnya sebagai bagian dari dinamika atau sejarah pemikiran.
Namun ketika ‘terpaksa’ berbicara tentang ateisme, saya melingkar membahas soal korupsi—perilaku yang kini sedang ‘naik daun’.
Menurut saya, dalam kebudayaan dan peradaban apa pun, perbuatan mencuri itu tabu, bahkan tercela. Ia menjadi pasal tersendiri dalam kitab-kitab hukum, dan siapa yang melakukannya, akan mendapat sanksi.
Dalam masyarakat, larangan mencuri adalah semacam pasal tak tertulis. Orang yang ketahuan mencuri akan memicu reaksi keras. Nasib pencuri bisa apes, dihajar warga, bahkan tanpa ampun. Jangankan perampok, pencopet kelas recehan saja bisa tak selamat.
Dalam pandangan budaya maupun agama, mencuri tak mendapat tempat. Orang berbudaya atau beragama tak akan melakukan perbuatan hina semacam itu. Mencuri biasanya hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar terdesak, atau mereka yang tak terdidik. Sebab keterdidikan—apa pun bentuknya, entah dari agama, budaya, atau nilai-nilai humaniora—tak akan membenarkan perbuatan mencuri.
Tapi hari-hari ini kita sedang berada di zaman yang ganjil. Di tengah kemewahan dan kecanggihan peradaban, mencuri bukan lagi dianggap tabu. Ia sekadar menjadi ‘peristiwa hukum’ yang tercerabut dari nilai moral, budaya, dan agama. Perbuatan hina itu kini dilakukan secara sadar, bahkan terencana. Pelakunya pun bukan orang yang terpaksa, tapi orang-orang terdidik, yang sudah ‘kenyang’ pendidikan formal. Bahkan tak jarang, mereka juga paham soal nilai-nilai agama dan budaya.
Hanya sedikit saja perbedaan antara mereka dan pencuri konvensional. Bedanya, pencuri zaman sekarang disebut koruptor. Korupsi jadi istilah yang ‘naik kelas’. Nilainya pun tak sebanding: jauh lebih besar, bisa ribuan bahkan jutaan kali lipat dari pencurian biasa.
Koruptor juga berbeda dalam hal nasib dan posisi. Mereka sering kali tak malu. Masih bisa tersenyum, melambaikan tangan ke publik saat ditangkap. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tetap mendapatkan penghormatan, bahkan menang dalam pemilu.
Padahal, apa bedanya mencuri dan korupsi? Sama saja. Inilah keanehan zaman baru.
Lalu, apa kaitannya dengan ateisme?
Jelas: pelaku korupsi pada hakikatnya menganggap Tuhan tidak ada. Atau, setidaknya, mereka tak mengakui bahwa Tuhan melihat dan mencatat perbuatan manusia. Sebab jika mereka benar-benar yakin, mustahil mereka berani melakukan perbuatan hina itu.
Secara logis, itulah ateisme yang nyata—meskipun tentu saja, mereka yang menyebut dirinya ateis belum tentu akan melakukan korupsi atau perbuatan tercela lainnya.
Lantas, apakah koruptor itu tidak percaya Tuhan? Saya tak tahu. Sekali lagi, itu soal hati. Tapi secara empiris, korupsi adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Tuhan. Di situlah letak keateisannya. Atau, mungkin memang ada jenis Tuhan yang berbeda. Tapi itu soal lain lagi.
(Juni 2021)
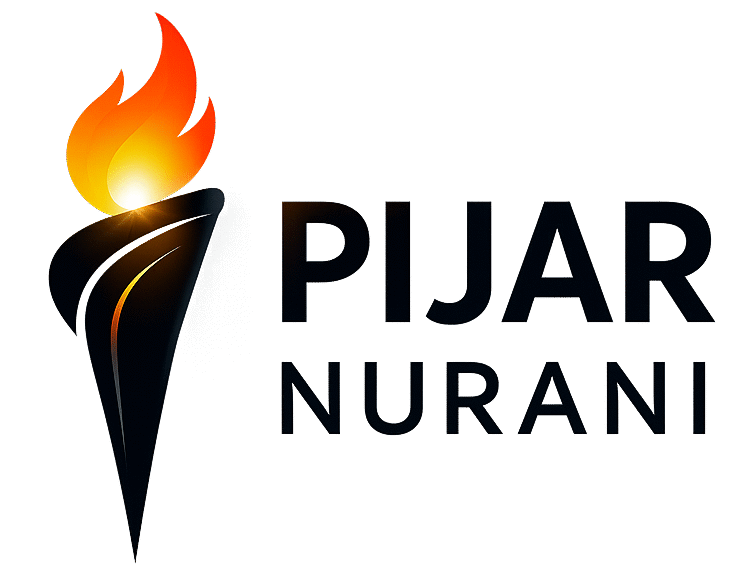






sgc3yu