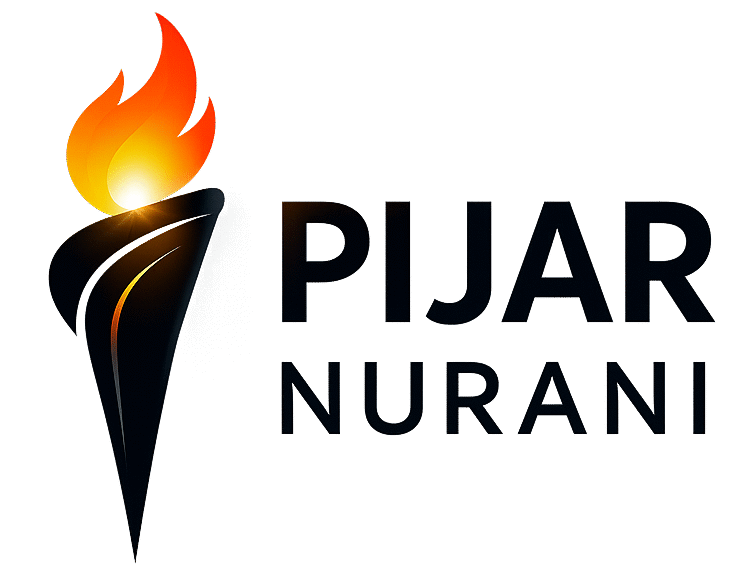Mencium Bau Surga

Mencium Bau Surga
“Boleh kukatakan sesuatu padamu?” kata Sandi pada Sania saat mereka duduk santai di teras rumah.
Sania yang semula duduk bersebelahan, kemudian berdiri menuju kursi di depan Sandi. Posisinya kini berhadapan. Sikap duduk Sania seperti memberi perhatian khusus. Tak biasa untuk utarakan sesuatu, Sandi mesti minta ijin. Mungkin ada hal penting ingin disampaikan.
“Kamu mau berkata apa sayang, bicaralah,” kata Sania dengan senyum manisnya seperti memberi kode suaminya untuk mulai bicara.
“Aku bahagia hari ini,” ucap Sandi dengan senyum dan raut wajah berseri.
Sania masih terdiam menanti kelanjutan Sandi bicara. Matanya tetap tertuju pada wajah suaminya.
“Sudah? Hanya itu yang ingin kamu katakan?”
Sandi menganggukkan kepalanya.
“Aku sudah duduk manis, siapkan telingaku untuk mendengar, kamu hanya ingin katakan itu?”
Dalam benak Sania, Sandi akan bicara panjang lebar ternyata hanya berucap pendek saja.
“Iya, aku hanya ingin katakan itu. Tak ada yang lain”
Sania beranjak dari kursinya dan berjalan dibelakang Sandi duduk. Tangannya merangkul ke leher Sandi dengan wajahnya diletakkan di bahu kanan suaminya.
“Kamu bahagia karena apa, sayang. Sepertinya istimewa sekali,” tanya Sania seperti hendak mewadahi kebahagiaan suaminya.
“Aku bahagia dengan kebersamaan ini,” kata Sandi sambil memegang tangan Sania.
“Bukannya tiap hari kita bersama. Bukannya tiap hari kita biasa ngobrol di sini, seperti ini, di teras ini?”
“Sebenarnya tiap hari pula aku ingin mengatakan rasa bahagiaku padamu,” kata Sandi melirikkan matanya ke wajah istrinya yang masih bertumpu ke bahu Sandi.
“Kamu itu seperti kita masih masa pacaran saja”
“Persis, ” sahut Sandi sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Sania, “..itu yang kurasakan saat ini”
“Wow.. masak sih?”
Sania kemudian kembali melangkah ke kursi depan Sandi. Posisi duduknya seperti ingin mendengar lebih jauh apa yang sesungguhnya dirasakan suaminya
“Sungguh Sania, suasana hatiku seperti saat dulu aku mendekatimu dan tak sabar mengatakan, I love you..”
“Oh ya?”
“Begitulah..”
“Sandi,” kata Sania mencoba menyelami perasaan suaminya lebih jauh, “…bukannya masa jatuh cinta itu telah lewat. Dua tahun kita menikah, masak sih, kamu masih membawa suasana seperti masa pacaran?”
“Karena aku sengaja menjaga dan merawatnya. Sampai sekarang,”
“Mengapa kamu melakukan itu?”
“Karena aku merasa bersyukur”
“Bersyukur karena apa?”
“Karena aku mendapatkanmu, bidadari cantik yang baik hati. Tuhan telah mengirimkannya untukku. Mana mungkin aku tidak mensyukuri?”
Sania tiba-tiba merasa haru oleh begitu besarnya cinta suaminya. Ia sangat tersanjung, walau menurutnya Sandi berlebihan melihatnya
“Tidak Sandi, aku yang merasa bersyukur mendapatkanmu. Keputusanku tepat. Kamu lelaki istimewa yang pernah kujumpai. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini karena mendapatkan limpahan cintamu,” ucap Sania dengan segenap perasaannya.
Kini Sania paham mengapa suaminya itu selalu tampak ceria bahagia ketika di rumah. Sania juga kini paham, mengapa Sandi punya banyak cara mengekspresikan cintanya, mulai tutur kata, pujian, hadiah dan bermacam tingkah laku, yang meski sederhana, tapi memberi pesan cinta. Dulu, itu dianggapnya sekedar sebuah kejutan untuk menyegarkan suasana saja. Kini ia percaya, Sandi sungguh-sungguh diliputi perasaan cinta yang besar.
“Tapi maafkan aku Sandi, jika aku tak bisa menjaga dan merawat cinta sepertimu” ucap Sania dengan rasa bersalah.
“Aku yang bisa menilai dan merasakan. Cintamu juga begitu besar padaku. Kamu lebih dewasa membawa cintamu.”
Tiba-tiba Sandi memegang jemari Sania dengan kedua tangannya. Matanya memandang wajah istrinya dengan penuh perasaan. Dipegang jemari tangannya, hati Sania tiba-tiba seperti bergolak. Ada getar rasa yang menjalar disekujur tubuh yang membuat jantungnya berdegub tak beraturan.
“Sania, ” kata Sandi perlahan. “..I love You. terima kasih atas semua ini, kamu membuatku bahagia”
Sania seperti tak kuasa lagi mendengar ucapan Sandi. Kata-kata itu seperti mengembalikan suasana saat pertama kali Sandi mengucapkannya. Badannya panas dingin. Mata Sania tampak basah berair oleh rasa haru yang mendalam.
“Sandi, semua tubuhku lemas. Aku sepeti tak kuasa manampung besarnya cintamu. Terima masih atas semua cintamu, I love you, too,” ucap Sania dengan terbata.
Sandi turut hanyut melihat keharuan di wajah isterinya. Dengan telunjuknya ia berusaha menghapus air mata yang mulai jatuh dari pelupuk mata.
“Jangan tahan tangismu, sayang. Air matamu adalah kata cinta dan kebahagiaan”
“Terima kasih Sandi, aku bahagia dan aku mengerti kebahagiaanmu sekarang”
Untuk beberapa waktu Sandi dan Sania terlihat hanyut dalam kebahagiaan. Keduanya kemudian sama-sama menikmati teh hangat dengan mata saling pandang seperti tak mau kehilangan momen kebahagiaan yang tampak di masing-masing wajah.
“Sandi, boleh kutanya sesuatu padamu?” tanya Sania usai mereda suasana emosional diantara mereka.
“Tentu, kamu mau katakan apa padaku”
“Karena besarnya cintamu itukah kamu tak pernah marah padaku”
“Kenapa itu kamu tanyakan?”
“Sepanjang bersamamu, aku tak pernah merasakan marahmu seperti umumnya pasangan dalam keluarga?”
“Itu masalahkah?”
“Normalnya manusia punya rasa marah dan selisih pandangan”
“Kamu mau bilang aku tak normal?”
“Tentu tidak sayang, aku hanya takut”
Wajah Sania berubah serius. Pertanyaan itu diucapkan sungguh-sungguh.
“Takut? Kenapa takut?”
“Jangan-jangan karena besarnya cintamu, kamu pendam amarahmu demi aku,” kata Sania menunjukkan sikap khawatir.
“Jika itu menumpuk dan menggumpal, suatu saat bisa meledak. Atau mungkin akan jadi penyakit. Aku tak mau itu terjadi,” sambung Sania seperti menegaskan kekhawatirannya.
Sandi tersenyum mendengar kerisauan Sania. Ia mencoba paham. Kekhawatiran itu wajar
“Sania, semoga itu tak akan terjadi. Mungkin aku belum punya alasan untuk marah”
“Sudah dua tahun kita menikah dan aku bukan perempuan sempurna yang terlepas dari salah. Banyak alasan kamu marah padaku”
Sandi tak langsung bereaksi. Ia raih cangkir teh yang masih tinggal separuh. Setelah diminum beberapa teguk, ia meletakkan kembali di atas meja.
“Marah itu pilihan, sayang,” kata Sandi memulai pembicaraan. “…selama ini aku berusaha mengatasi masalah tanpa harus marah. Menurutku marah itu merusak kebahagiaan”
Sania mengangguk mencoba untuk paham.
“Lagian, terlalu sayang aku marah sama pujaan hatiku”
“Aku serius Sandi,”
Sania dengan gaya manjanya mencubit lengan Sandi.
Sudah biasa, kalau Sania gemas, lengan Sandi jadi korban cubitan. Jika saja cubitan itu menampakan bekas, mungkin sudah puluhan atau ratusan jumlahnya.
“Aku juga serius, swer!” kata Sandi sambil.memegang bekas cubitan Sania.
“Apalagi yang kamu takutkan?” sambung Sandi dengan wajah dibuat serius.
Sania memperbaiki posisi duduknya. Kali ini ia merebahkan tubuhnya disandaran kursi sehingga terlihat lebih santai.
“Apakah nanti kamu lakukan juga pada anak-anak kita?” tanya Sania sambil memegang perutnya yang makin buncit.
“Tentu”
“Mungkinkah membesarkan anak di zaman sekarang tanpa rasa marah orang tua?”
“Sania, ” kata Sandi mencoba mengutarakan pikirannya, “Setiap marah itu selalu meninggalkan luka, terlepas dari benar atau salah. Aku tak ingin membesarkan anak-anak kita dengan jejak luka. Marah itu cara dan harus digunakan dalam posisi yang amat mendesak. Jika tanpa marah semua bisa terarah, kenapa mesti marah?”
Sania kembali menganggukkan kepalanya. Sandi selalu punya penjelasan yang acap kali sulit di tolak.
“Aku ingin membesarkan anak-anak kita dengan cinta dan kebahagiaan,” sambung Sandi.
“Seyakin itu kita mampu?”
Sandi kembali meraih jemari Sania dan memegangnya erat, “Kita harus mampu, Sania. Aku mengajakmu. Keluarga kita harus dipenuhi cinta. Hidup dalam cinta. Hanya dengan cara itu kita mampu melawan zaman”
“Mengapa begitu, Sandi?”
“Karena zaman ini tak punya hati dan cinta”
Sania mengangguk mendengar kesungguhan dan keseriusan Sandi.
“Kamu imamku, Sandi. Kemana jejakmu, aku aku mengikutimu. Aku percaya kamu. Bimbing aku…”
“Sania, jika kamu merelakan cintamu, dan aku merelakan cintaku, untuk kita, keluarga kita dan kehidupan ini. Percayalah, bau surga ada di rumah ini. Aku percaya, bahan baku surga itu dari cinta. Dari cinta Tuhan untuk hambanya, bismillah…”
Sania makin tak bisa berkata-kata. Sandi bicara dengan pikiran dan hati yang dalam.
“Sandi, bawa cintaku pada cintamu, beserta harapan dan mimpi-mimpimu. Karena Aku juga mencium bau surga itu”
Di teras sore itu. Tangan Sandi dan Sania saling berpegang erat. Kedua matanya saling pandang. Meski tanpa kata, pesan yang mengalir dari kebersamaan itu adalah tekat hidup bersama dalam ikatan cinta.
Nov, 2023