Orang Tua Feodal: Pantaskah?

Orang Tua Feodal: Pantaskah?
Dalam banyak keluarga, kita masih menjumpai pola relasi orang tua dan anak yang bercorak feodal. Orang tua — terutama ibu — diposisikan laksana ratu dalam rumah tangga: diagungkan, disakralkan, dan diberi ruang istimewa. Mereka duduk dalam takhta simbolik sebagai pusat keputusan dan kebenaran. Ini bukan hanya soal penghormatan, melainkan telah menjelma menjadi bentuk kuasa yang tak jarang dipraktikkan secara otoriter.
Sikap feodal itu terlihat ketika orang tua menganggap posisi sebagai orang tua adalah posisi di atas, yang otomatis layak ditaati tanpa perlu diuji logika atau moralitasnya. Mereka merasa berhak mengatur apa saja, memerintah apa saja, bahkan menilai hidup anak secara mutlak, hanya karena mereka telah “melahirkan” dan “memelihara sejak kecil”. Kebaikan yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua dalam membesarkan anak, berubah menjadi alasan untuk menagih, menuntut, bahkan mengontrol hidup anak sepanjang hayat.
Orang tua feodal sering menganggap penghormatan anak sebagai sesuatu yang bisa diminta, bahkan ditagih. Padahal, penghormatan sejati tidak lahir dari tekanan atau tuntutan. Ia tumbuh dari ketulusan, dari rasa hormat yang muncul karena kasih sayang, perhatian, dan kehadiran yang nyata. Memelihara anak bukan jasa, melainkan kewajiban. Dan anak tidak pernah memilih untuk dilahirkan, apalagi meminta dibesarkan dengan syarat akan membalas budi di masa depan. Jika pun anak menghormati orang tua, itu adalah bentuk dharma — kewajiban batiniah yang bersumber dari cinta dan kesadaran, bukan hutang sosial yang bisa ditagih dengan suara tinggi.
Yang lebih menyedihkan, dalam banyak kasus, orang tua yang merasa berhak ditinggikan justru sering kali lalai dalam menjalankan peran mendasar mereka: mendidik, merawat, hadir secara emosional. Banyak anak tumbuh dalam rumah yang tidak ramah, tidak suportif, bahkan penuh kekerasan verbal dan emosional. Akibatnya, anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi dewasa yang membawa luka batin mendalam. Mereka mengalami gangguan kepercayaan diri, ketakutan akan otoritas, hingga kesulitan membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Luka-luka masa kecil itu membentuk beban psikologis jangka panjang — mulai dari kecemasan, depresi, hingga pola relasi yang toksik.
Dari data yang tersedia, kita juga melihat tingginya angka fatherless — anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran atau figur ayah yang sehat — serta meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Ini bukan semata-mata akibat zaman atau pergaulan, tapi juga cermin dari kegagalan kolektif orang tua dalam menjalankan “profesi” sebagai pendidik pertama dalam rumah. Maka, tak heran jika kini banyak anak berani “melawan” orang tuanya. Itu bukan semata karena anak durhaka, tapi karena selama ini mereka mungkin tidak pernah benar-benar dididik dengan cinta dan keteladanan. Yang mereka alami adalah bentakan, tekanan, dan perintah tanpa ruang untuk berdialog.
Tulisan ini tidak bermaksud meruntuhkan martabat orang tua. Justru sebaliknya: ini adalah pengingat agar orang tua tidak semata-mata menuntut, tapi juga mengoreksi diri. Penghormatan itu tidak dibangun dengan suara keras atau narasi “orang tua selalu benar”, tapi dari komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan dharma sebagai ayah dan ibu: membesarkan anak dengan kasih, membimbing dengan bijak, dan hadir dengan penuh cinta.
Orang tua yang sejati adalah mereka yang tak perlu meminta dihormati, karena sikap dan cintanya membuat anak bersimpuh dalam hormat tanpa diperintah. Sebaliknya, orang tua feodal hanya akan melahirkan generasi yang resah — yang tumbuh dewasa dengan luka tersembunyi, dan tak lagi tahu bagaimana mencintai rumah serta orang yang seharusnya menjadi pelindung paling awal.
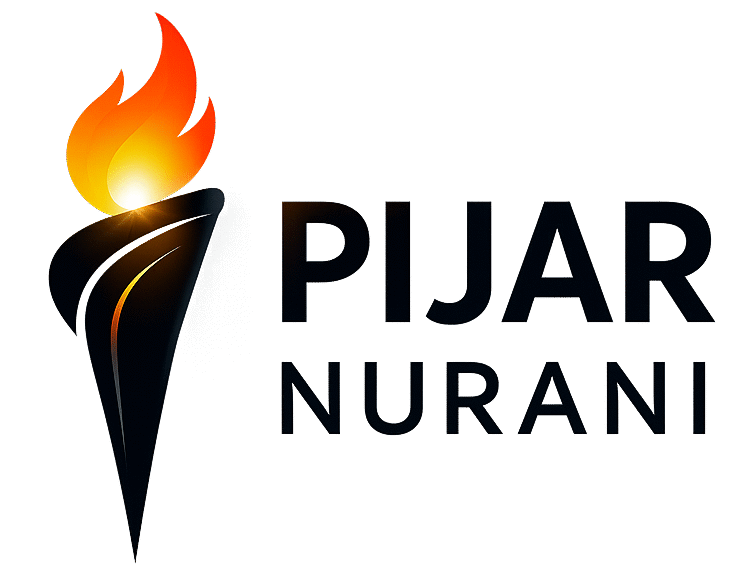






https://shorturl.fm/03TD8
https://shorturl.fm/ik9cg
https://shorturl.fm/eQCRP
https://shorturl.fm/IY54A
https://shorturl.fm/v5CJs
https://shorturl.fm/wddUR