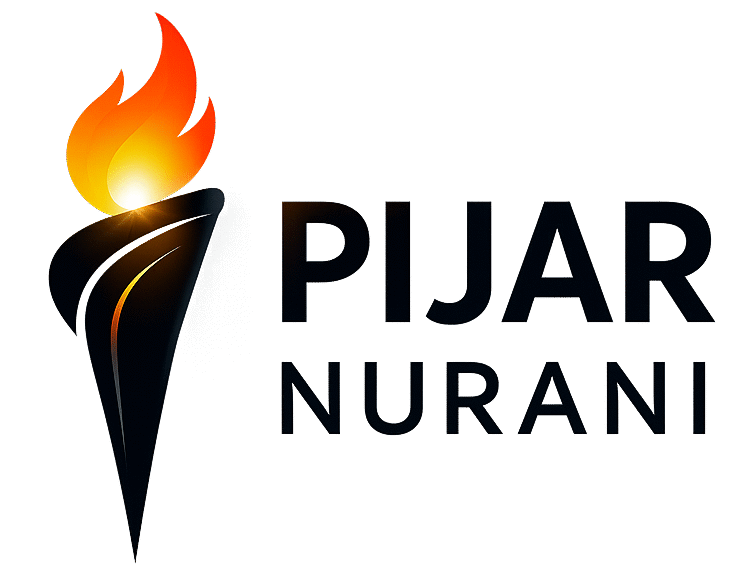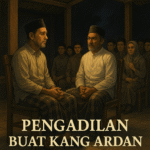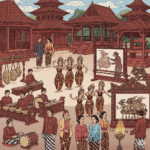Pembangunan & konsolidasi budaya
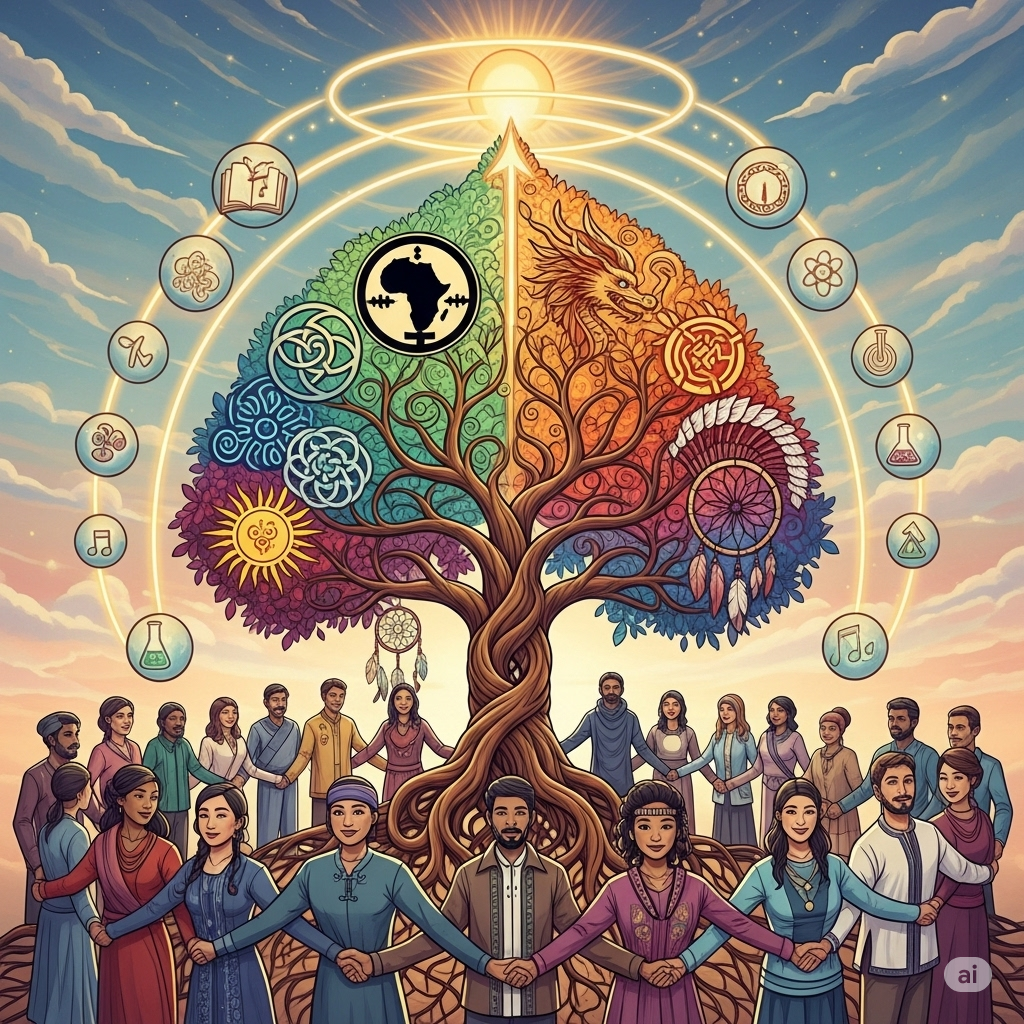
Saya memulai tulisan ini dengan sedikit mencuplik sejarah Perang Diponegoro. Perang ini disebut juga dengan perang Jawa, karena melibatkan rakyat dibanyak daerah di pulau Jawa. Terjadi pada Tahun 1825-1830.
Al kisah, VOC kesulitan menghadapi Perlawanan Pangeran Diponegoro. Masyarakat Jawa yang dikenal lembut dan santun tiba-tiba menjadi ksatria tangguh di berbagai medan perang. Mereka militan dan rela berkorban nyawa demi membela pemimpinya.
Lima tahun berlalu, dengan segenap kekuatan senjata dan logistik, putra sulung Hamengkubowono tiga itu tak kunjung bisa dikalahkan. Termasuk dengan cara membangun ratusan benteng stelsel untuk mempersempit ruang gerak Sang Pangeran. Namun, tetap saja Diponegoro tak terkalahkan. Upaya penculikan sang pangeran juga kerap dilakukan, tapi selalu gagal.
Singkat cerita, akhirnya VOC menggunakan senjata lain bernama kebudayaan.. Melalui seorang Ahli Budaya, VOC mendapatkan saran untuk melakukan diplomasi budaya. Dengan cara yang penuh hormat, akhirnya VOC berhasil mengundang Pangeran Diponegoto untuk berunding sehingga ‘sang pemberontak’ itu keluar dari sarang persembunyian dengan suka rela. Dengan tipu muslihat akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dalam perundingan itu dan diasingkan hingga wafat.
Itulah pendekatan budaya yang dilakukan VOC setelah seluruh kekuatan logistik, pasukan dan persenjataan ternyata gagal dilakukan. Melalui pendekatan budaya, VOC tahu tata nilai dan perilaku lawan, serta tahu bagaimana cara memperlakukan dan mengalahkan lawan tanpa harus mengerahkan biaya yang besar. Pemahaman tepat atas pandangan budaya, membuat penakhlukan berjalan efektif.
Kisah Diponegoro di atas untuk memberi pesan betapa pentingnya penguasaan budaya untuk berbagai keperluan. VOC menggunakannya untuk keperluan penaklukan. Pun Belanda menggunakan strategi yang sama untuk menaklukkan Aceh.
Orde baru dalam beberapa kebijakannya juga memanfaatkan strategi budaya dalam rangka menggerakkan roda pembangunan. Salah satu contoh dalam hal ini adalah program Keluarga Berencana (KB). Program itu sukses dan diakui sebagai yang terbaik di dunia.
Suharto paham bahwa program penjarangan dan pembatasan kelahiran itu dalam banyak hal bertentangan dengan pandangan yang dianut masyarakat. Jika program itu dijalankan begitu saja, dan dijalankan oleh aparat pemetintah, mungkin akan terjadi resistensi warga. Justru kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Melalui pendekatan budaya, Orde Baru mengajak banyak tokoh masyarakat untuk berperan serta. Kehadiran tokoh, selain karena kepercayaan warga, mereka memiliki bahasa yang bisa diterima masyarakat. Para tokoh tak hanya menjadi juru bicara program KB, lebih dari itu mereka memberikan edukasi, pengertian-pengertian serta pemahaman yang bisa diterima masyarakat. Ada jembatan yang harus dilalui antara warga dan progran KB, yakni melibatkan pihak yang diterima dan dipercaya masyarakat.
Setelah waktu berlalu, program KB berjalan dengan baik. Bahkan ketika dicanangkan program KB mandiri, masyarakatpun mengambil inisiatif secara mandiri. Partisipasi masyarakat pada akhirnya membuat program KB berjalan sukses.
Terlepas dari banyak kelemahan rezim orde baru, ada banyak kebijakan dan program yang menyentuh rakyat secara langsung. Kehadiran negara sampai bawah dirasakan oleh masyarakat. Petani dan pertanian salah satu sektor yang mendapat perhatian hingga mengantarkan Indonesia pernah alami Swasembada pangan.
Secara esensi, pembangunan itu untuk manusia. Demi kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Siapapun pemimpinnya akan cenderung mengarah ke sana. Namun upaya mengarah ke situ haruslah dipahami terlebih dahulu tentang konsep manusia seperti apa yang akan menjadi obyek sekaligus subyek pembangunan. Setiap bangsa punya ciri dan coraknya sendiri yang berbeda satu dengan lainnya.
Patut untuk dicatat bahwa pandangan atas manusia, tentang siapa dirinya dan tentang apa yang dianggap penting untuk di tuju, termasuk tentang apa arti dan makna sejahtera, ada di dalam kebudayaan. Masing-masing budaya punya otonomi sendiri dalam memberi tafsir, pemahaman dan pemaknaannya sendiri tentang hidup dan kehidupan.
Pada kontek ini tak ada konsep pembangunan yang berlaku untuk semua (universal). Gagasan pembangunan harus berada pada radius budaya dimana ia akan diletakkan. Hanya dengan cara itu setiap kebijakan dan program pembangunan akan selaras dengan suasana batin masyarakat. Keselarasan ini akan mendorong keberterimaan dan partisipasi masyarakat luas.
Pada prakteknya, banyak program pembangunan berasal dari atas yang mengucur ke bawah tanpa hirau dinamika budaya. Pembangunan bekerja dengan caranya sendiri dan dengan ukurannya sendiri. Sebetapapun canggihnya sebuah program tersebut, dan sebetapapun telah banyak yang dilakukan serta besarnya anggaran yang dikeluarkan. Situasi itu tak lebih hanya menjadi ‘benda asing’ bagi masyarakat jika hal itu tidak masuk dalam jantung kebudayaan. Posisi masyarakat bisa jadi hanya menjadi penonton dan tak memicu partisipasi.
Oleh karena itu sebelum sebuah konsep pembangunan di rancang, menjadi penting untuk memahami intisari sebuah kebudayaan. Dalam hal ini sebenarnya, upaya memahami kebudayaan tak lain adalah memahami diri sendiri, memahami tentang siapa kita hari ini sebagai sebuah bangsa yang dibesarkan dan dibentuk oleh sejarah panjang. Tentang sampai di mana saat ini kita berada telah menggunakan kebebasannya sebagai sebuah bangsa yang menentukkan arah dan tujuannya sendiri.
Membaca kebudayaan, atau upaya mengerti diri sendiri akan menyangkut persoalan yang kompleks. Ini terjadi karena pertama, sebagai sebuah bangsa kita punya alam kebudayaan yang beragam dengan spektrum yang lebar. Dalam terma sosiologi, potret diri bangsa Indonesia berada dalam rentang gelombang 1,0 hingga 4.0. Tentu, keadaan itu punya keragaman yang tak mungkin disatukan. Membangun infra struktur megah di tengah masyarakat yang masih bertumpu pada kekuatan alam akan pasti salah alamat.
Kedua, dari sisi ekonomi, jurang ketimpangan yang begitu lebar masih menjadi fakta tak terhindarkan. Ketimpangan ini bukan semata soal ketidakadilan dan kemerataan, tapi soal kebersamaan sosial sebagai sebuah bangsa tidak tumbuh. Orang semakin memikirkan kepentingan sendiri dan tak peduli serta tak emphati dengan yang lain. Pembangunan harus mendorong kebersamaan sosial sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa. Perasaan bersaudara antar seluruh warga bangsa akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan bangsa.
Ketiga, gerakan modernisasi yang makin menguat dan ekspansif. Apapun megah dan kemilaunya modernisasi, ia lahir dari konstalasi sejarah dan budaya suatu bangsa. Alam modern bukan semata soal ilmu dan teknologi, melainkan juga soal nilai-nilai dan cara pandang kehidupan. Ada kebudayaan di balik modernisasi tempat ia lahir, tumbuh dan berkembang.
Meski laju modernisme tak terelakkan dan menggilas banyak sendi-sendi tradisi, itu bukan berarti sesuatu yang harus diterima dengan sendirinya. Hal paling fundamental dari tergerusnya tradisi adalah pudarnya identitas yang ikut serta didalamnya adalah seluruh bangunan kebudayaan yang membentuknya. Pudar atau pupusnya identitas membuat seseorang (masyarakat) kehilangan jatidiri. Hilang atau pudarnya jatidiri artinya ia menjadi bukan siapa-siapa. Sementara untuk menjadi sosok jatidiri baru (sosok modern sepenuhnya) bukanlah hal mudah, kalau tak boleh dibilang muskil.
Keempat, krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Kerelaan, kesetiaan dan militansi rakyat dalam perang Jawa, tak lepas dari wujud kepercayaan terhadap pemimpinnya, yakni Pangeran Diponegoro beserta orang kepercayaannya. Tanpa kepercayaan itu akan sulit terjadi mobilasasi dan partisipasi masyarakat tercipta. Sama halnya dengan tercapai kemerdekaan dan terbentuknya negara republik. Tanpa ada kepercayaan pada para pemimpin, hampir mustahil mendapatkan dukungan rakyat secara luas sehingga bangunan republik terwujud.
Sebuah tantangan besar hari ini adalah terjadinya krisis kepemimpinan. Bangsa ini berada dalam keadaan dimana banyak pemimpin alami cidera moral dan integritas. Banyaknya kasus pelanggaran moral dan hukum yang dilakukan oleh para pimpinan negara, baik dipusat maupun daerah sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada pemimpinnya. Keadaan ini akan membuat rakyat apatis terhadap apa kata atau ajakan pemimpin. Mobilitas dan partisipasi rakyat akan sulit terjadi ketika kepercayaan terhadap pemimpin telah pudar.
Dari pandangan tersebut di atas, pemilu menjadi salah saru momentum penting untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal penting yang patut dilakukan adalah pertama, sosok pemimpin baru harus mampu merebut kembali kepercayaan rakyat. Dimulai dari pemimpin tertinggi harus mampu menunjukan segala sikap dan sifat yang mendorong kepercayaan rakyat. Selanjutnya, kepercayaan itu harus pula didorong pada pemimpin lain yang memiliki posisi strategis masyarakat, baik dipusat maupun daerah. Upaya merebut kepercayaan pada pemimpin publik ini akan menjadi separoh keberhasilan dalam merealisasikan program pembangunan.
Kedua, perlunya melakukan konsolidasi budaya. Selama ini, modernisasi, yang menjadi tulang punggung pembangunan, cenderung meratakan dan menyeragamkan kebijakan serta ukuran-ukuran keberhasilan. Konsep pembangunan kita hampir sepenuhnya bertumpu pada ukuran-ukuran ekonomi yang material sifatnya. Gagasan pembangunan belum bisa masuk ke dalam kebudayaan dan melihat dari dalam tentang apa yang sesungguhnya bermakna bagi masyarakat. Tipologi masyarakat kita tidak sepenuhnya menempatkan materi sebagai sesuatu yang menarik dan unggul. Kebermaknaan masyarakat tidak sepenuhnya melekat pada yang materi. Inilah problem utama gagasan pembangunan (modernisasi).
Kita sebagai sebuah bangsa karena latar belakang sejarah dan budaya. Perlu dilakukan konsolidasi budaya, yang selama ini telah tercerai berai karena berbagai kebijakan/program yang sifatnya penyeragaman. Dari situ perlu dirumuskan kembali apa yang menjadi kehendak-kehendak rakyat yang tak hanya soal pemenuhan materi tetapi juga batin.
Satu hal penting yang cukup fundamental adalah para pemimpin tidak boleh melihat budaya sebagai obyek yang berjarak dari kebijakan. Kebudayaan harus dilihat sebagai subyek yang secara kolektif hendak melakukan usaha bersama menuju masa depan berdasarkan modal sosial, sejarah dan budaya yang dimiliki.
Itulah makna makna kemerdekaan direbut agar supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas (pembukaan UUD 45 alinea 3). Bebas menentukan arah dan tujuan serta cara-cara menempuhnya, tanpa harus didekte oleh pihak lain. Segala bentuk unsur yang datang dari luar hanya bersifat referensial. Tak lebih dari itu.