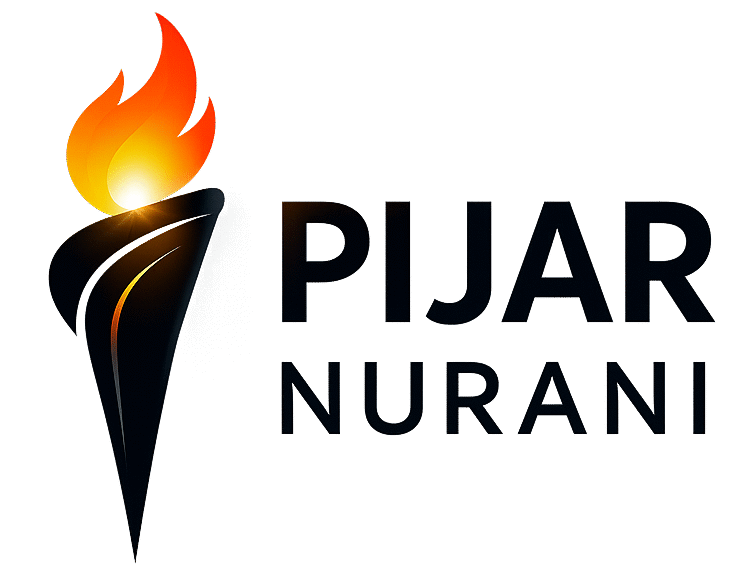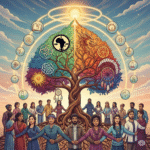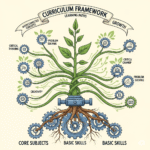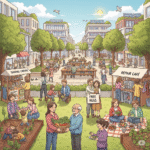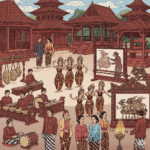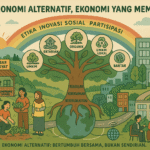Pendekatan Budaya Dalam Pembangunan

Pendekatan Budaya dalam Pembangunan
Pembangunan pada hakikatnya bukan sekadar urusan teknis atau persoalan ekonomi, melainkan juga sebuah proses kultural. Sebuah program pembangunan tidak akan efektif jika hanya dilihat sebagai proyek fisik, angka-angka pertumbuhan, atau indikator material lain. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu agenda sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu berakar pada kebudayaan masyarakat yang hendak dibangun.
Sejarah kolonialisme memberikan pelajaran penting tentang hal ini. Para orientalis—ilmuwan Barat yang menekuni studi ketimuran—mempelajari budaya masyarakat jajahan dengan sangat serius. Bukan semata karena motif ilmiah, melainkan demi kepentingan politik penaklukan. Pengetahuan tentang bahasa, adat, agama, dan sistem nilai lokal dijadikan senjata non-militer untuk menundukkan perlawanan rakyat.
Contoh konkret terlihat pada Snouck Hurgronje di Hindia Belanda. Ia menyelami tradisi dan kehidupan keagamaan masyarakat Aceh, lalu memberikan rekomendasi politik kepada pemerintah kolonial: membedakan antara Islam ritual yang boleh berkembang dan Islam politik yang harus ditekan. Strategi ini terbukti efektif dalam meredam perlawanan. Di India, Inggris menggunakan studi hukum Hindu dan Islam untuk merancang sistem peradilan kolonial yang memudahkan kontrol atas masyarakat. Prancis, dalam ekspedisi Napoleon ke Mesir, bahkan membawa rombongan sarjana untuk memetakan kebudayaan, sejarah, dan geografi Mesir, sehingga ekspansi militer berjalan seiring dengan dominasi pengetahuan.
Jika untuk menjajah saja diperlukan penguasaan pengetahuan budaya, maka untuk membangun bangsa sendiri kebutuhan itu jauh lebih mendesak. Agenda pembangunan tanpa memahami karakter masyarakat ibarat menanam pohon tanpa mengenal tanahnya: tumbuhnya akan rapuh, mudah goyah, dan tidak berumur panjang.
Pendekatan budaya menuntut agar setiap kebijakan pembangunan terlebih dahulu menyelami suasana batin masyarakat—nilai-nilai, cara pandang, tradisi, serta harapan kolektif yang hidup di dalamnya. Pembangunan yang peka budaya akan lebih mudah diterima karena dipandang sebangun dengan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kebijakan yang asing dari konteks kultural cenderung menimbulkan penolakan, resistensi, bahkan kegagalan.
Dalam pandangan Soedjatmoko, “pembangunan hanya akan berhasil apabila ia tumbuh dari kebudayaan bangsa itu sendiri, bukan dipaksakan dari luar.” Pandangan ini menegaskan bahwa kebudayaan adalah fondasi pembangunan, bukan sekadar hiasan. Senada dengan itu, Ki Hadjar Dewantara sejak lama mengingatkan bahwa “kebudayaan adalah buah budi manusia yang hidup, yang menjadi puncak kemajuan bangsa, dan tidak dapat dilepaskan dari pendidikan serta pembangunan.” Dengan kata lain, pembangunan harus sejalan dengan denyut kebudayaan agar mampu memuliakan manusia dan bangsanya.
Selain itu, hasil pembangunan tidak semestinya hanya diukur dengan indikator material seperti pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, atau panjang jalan raya. Ukuran yang lebih esensial adalah sejauh mana pembangunan itu memperkuat identitas budaya, memberi makna baru yang relevan bagi masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi kolektif. Dengan kata lain, pembangunan yang berhasil bukan hanya yang menghasilkan benda, tetapi yang menyalakan semangat, memperkokoh nilai, dan menghidupkan gairah untuk bergerak maju bersama.
Maka, pembangunan berperspektif budaya adalah sebuah keniscayaan. Ia mengingatkan bahwa bangsa ini memiliki kekhasan dan karakteristik unik yang harus dijadikan dasar pijakan. Mengabaikannya sama saja dengan meniadakan sumber daya terbesar yang dimiliki: kekuatan jiwa dan kearifan masyarakat itu sendiri. Dengan cara pandang ini, pembangunan tidak hanya mencetak infrastruktur, tetapi juga membangun peradaban.